Aliansi Terlibat Bersama Korban Geothermal Flores Surati Gubernur NTT Melki Laka Lena
ENDE : WARTA-NUSANTARA.COM– Aliansi terlibat Bersama Korban Geothermal Flores (ALTER BKGF) menyurati Gubernur NTT, Melki Laka Lena untuk menyetakan menolak laporan Tim Satuan Tugas (Satgas) Panas Bumi Flores dan Lembata.

Mengawali surat ke Gubernur NTT yang juga diterima Warta-Nusantara.Com, Rabu, 23 Juli 2025, menyatakan, Pertama-tama, perkenankan kami memperkenalkan diri. Kami sekelompok aktifis yang peduli dengan Lingkungan dan Pangan, yang tergabung dalam Aliansi TERLIBAT Bersama KORBAN Geothermal Flores (ALTER BKGF) di antaranya Forum Pemuda Peduli Lingkungan Hidup Paroki Roh Kudus Mataloko, Forum Peduli Keutuhan Lingkungan Berdampak Geothermal Paroki Santo Yoseph Laja, Komisi Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan SVD Provinsi Ende [JPIC SVD Ende], Komisi Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan SVD Provinsi Ruteng [JPIC SVD Ruteng], Komisi Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan OFM [JPIC OFM], Komisi Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan Keuskupan Agung Ende [JPIC KAE], Badan Eksekutif Mahasiswa IFTK Ledalero. Inilah isi surat selengkapnya.

Menanggapi laporan Tim Satgas Masalah Panas Bumi Flores Lembata (selanjutnya disebut Tim
Satgas) yang dibentuk Pemda NTT, ALTER BKGF mengapresiasi kebijakan tersebut. Meskipun
demikian, ALTER BKGF menggugat dan menolak laporan hasil evaluasi tersebut karena :
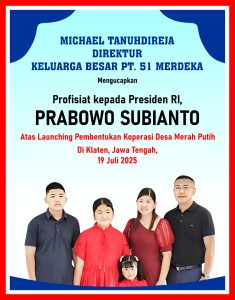
Pertama, hasil evaluasi satgas yang tidak mencerminkan realitas lapangan.
Kedua, partisipasi Masyarakat sipil yang tidak memadai dalam Tim Satgas geotermal.
Ketiga, proses pengusulan keanggotan tim yang tertutup dan tanpa melibatkan usulan stakeholder yang relevan, termasuk usulan anggota komunitas yang terkena dampak langsung dan tidak langsung, serta menolak
pembangunan pembangkit listrik panas bumi (PLTP).
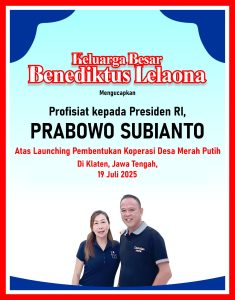
Keempat, metode penilaian yang tidak cukup mengakomodasi suara warga yang menolak, termasuk suara kaum perempuan. Kelima, waktu kunjungan yang sangat singkat dan terbatas sehingga tidak mampu menggali kegelisahan sosial akibat proyek panas bumi dan keenam, keraguan akan independensi Tim Satgas karena
diawasi dan dibiayai oleh pihak yang tidak netral dalam konflik dan permasalahan pembangkit panas bumi.

ALTER BKGF mendukung proses transisi energi yang memenuhi prinsip-prinsip keadilan sosial
dan ekologis, mendorong demokrasi energi dan kedaulatan energi komunitas.
ALIANSI TERLIBAT Bersama KORBAN Geothermal Flores
[ALTER BKGF]
Alamat: Jl. Durian No. 12 Kel. Mautapaga-Kec. Ende Timur, Kab. Ende-Flores-NTT
Koordinator: P. Dr. Felix Baghi, SVD, Ko-Koordinator: Ir. Justin Coupertino, Sekretaris: Josef San Dou (Chicago)
Komisi Hukum: Marsellinus Ado Wawo, SH, Vincentius Repu, Komisi Pendidikan & Analisa Data: Wilfridus Leba,
RD. Reginaldus Piperno, Komisis Networking & Koalisi: P. Paul Rahmat, SVD (New York), P. Martinus Bhisu,
SVD (Paraguay), Rev. Lukas Jua, SVD, Komisi Sosial: Gabriel Goa
2
Demikian tanggapan ALTER BKGF terhadap laporan Tim Satgas panas bumi Flores-Lembata. Untuk penjelasan lengkapnya dapat dilihat di lampiran. Atas perhatian diucapkan terima kasih.
Surat tersebut ditanda tangani oleh : P. Dr. Felix Baghi, SVD Ir. Justin Coupertino Umbu Lede Koordinator Ko-Koordinator, Marselinus Ado Wawo, SH Wilfridus Leba, SE Komisi Hukum Komisi Pendidikan & Analisa Data, RD. Reginaldus Piperno P. Ignas Ledot, SVD, Ketua, JPIC Keuskupan Agung Ende Ketua, JPIC SVD Ende, P. Yansianus Fridus Derong, OFM Sr. Wilhelmina Kato, SSpS, Ketua, JPIC OFM Indonesia Ketua, JPIC SSpS Flores Bagian Timur, Klemens Makasar P. Simon Suban Tukan, SVD, Direktur, PADMA Indonesia Ketua, JPIC SVD Ruteng.
Penjelasan Mendasari Penolakan Alter KGF Atas Hasil Kerja Tim Satgas Panas Bumi Flores dan Lembata
A. Tentang Isi Laporan Hasil Evaluasi Tim Satgas Panas Bumi
1. Klaim dukungan mayoritas masyarakat di lokasi terhadap proyek pembangkit panas bumi adalah generalisasi prematur. Tim Satgas gubernur NTT melaporkan bahwa dukungan warga pada proyek panas bumi merupakan suara mayoritas. Klaim ini muncul dalam laporan kunjungan Sokoria, Lembata dan lokasi lain. Komunikasi ALTER BKGF dengan warga di lokasi menunjukkan bahwa
dukungan pada proyek rata-rata berasal dari kelompok yang telah menerima ganti rugi lahan dari PLN atau dari Perusahaan pembangkit independent yang terikat kontrak dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN). Di Atadei, Lembata, kelompok pendukung justru masih memiliki keraguan yang tercermin dari permintaan sosialisasi ulang, penjelasan komprehensif tentang dampak PLTP dengan melibatkan semua pihak, terbuka dan demokratis.
Dengan demikian, klaim dukungan mayoritas warga pada PLTP merupakan generalisasi prematur oleh tim akademisi dalam Satgas yang disebut profesional oleh gubernur. Tim
juga mengabaikan realitas bahwa di semua lokasi pembangkit terjadi penolakan sejak awal pembangunan. Generalisasi prematur di atas melanggar prinsip-prinsip obyektivitas dan norma-norma kejujuran akademis, dan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tidak berbasis fakta empiris.
Reaksi penolakan warga di semua lokasi panas bumi FloresLembata, atas laporan Tim Satgas, menunjukkan klaim dukungan, tidak berdasar pada realitas lapangan, tetapi asumsi prematur.
2. Deligitimasi dan Ekslusi Suara Korban Pembangunan PLTP dan yang menolak PLTP. Laporan Satgas ini menegasi problem yang disuarakan oleh kelompok masyarakat
adat yang menolak PLTP. Tim satgas gagal menangkap akar penyebab dari kegelisahan sosial dan penolakan terhadap PLTP. Akar penyebab adalah ketidakadilan akses pada ruang hidup, ketidakdilan akses pada sumber daya tanah, air, hutan dan ruang sosial budaya, ketidakadilan prosedural dan informasi yang jujur dan terbuka melalui sosialisasi yang partisipatif, demokratis dan representatif. Di semua lokasi PLPT, proses Penerapan Prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) bagi Masyarakat Adat, berjalan dalam pola selektif, diskriminatif, partisipasi terbatas. Tim satgas gagal menangkap realitas ini dalam laporan.
Di Atadei dan Sokoria pertemuan hanya melibatkan tokoh dan pemilik lahan yang mendapat ganti rugi. Di Sokoria, persetujuan warga diperoleh dengan menggunakan intimidasi. Di Wae Sano, korporasi hanya melibatkan mereka yang mendukung dan sebagian besar berasal luar kawasan yang bersentuhan langsung dengan pembangkit.
Di Poco Leok, pertemuan langsung dengan warga hanya berlansung 2-3 kali. Pertemuan-pertemuan lain berlangsung di luar komunitas yang ruang hidupnya menjadi tempat eksplorasi PLTP. Deligitimasi dilakukan dengan mengekslusi suara warga yang menolak Pembangkit Panas Bumi.
Laporan Tim Satgas mereduksi penolakan sebagai persoalan “kurangnya pengetahuan” yang membatalkan proses dialog. Sikap ini memperjelas ciri anti-politik dari
intervensi pemerintah dalam merespon tuntutan warga adat dan gereja. Bagi kami, kegagalan dialog adalah simptom dari problem rekognisi dan representasi di mana tuntutan atau agenda warga sejak awal dieksklusi dalam proses kebijakan pembangunan pembangkit panas bumi. Yang terjadi adalah tuntutan politik warga yang menolak sejak awal dicegah untuk menjadi kebijakan publik. Ruang argumentasi dikondisikan hanya untuk menampung agenda resmi pemerintah. Dengan kata lain, kalaupun selama ini ada dialog atau forum partisipasi yang diselenggarkan negara, forum tersebut telah membatasi
agenda-agenda kebijakan mana yang diakui dan mana yang ditolak.
3. Subordinasi pengetahuan dan kemampuan belajar komunitas. Laporan Satgas melihat salah satu akar dari konflik dalam pembangunan geotermal adalah masalah “lack of knowledge” (kekurangan pengetahuan) tentang manfaat dan ‘keindahan’ energi panas bumi. Keyakinan Tim Satgas bahwa warga kurang pengetahuan tercermin dari adanya rekomendasi Tim bahwa perlu ada sosialisasi lanjutan untuk mengatasi ketimpangan informasi (Sokoria), studi banding (Mataloko & Lembata), dan sosialisasi lanjutan (Mataloko, Sokoria, dan Nage). Rumusan masalah yang dikonstruksi tim ini menegaskan kecendrungan menempatkan lebih rendah pengetahuan Masyarakat dari pengetahuan yang dimiliki sains modern dan yang menjadi sumber legitimasi negara. Pengetahuan modern
dianggap lebih bisa dipercaya daripada pengetahuan masyarakat akan ruang dan konsepsi mereka tentang livelihood.
Cara pandang ini mengabaikan tiga hal. (a) warga memiliki
pengetahuan kolektif tentang lingkungan, ruang hidup mereka dan relasi ekonomi, sosial dan budaya yang menjadi bagiannya. Pembangunan PLTP dilihat sebagai pemenggalan keutuhan ruang hidup. Ini mendasari penolakan di semua lokasi. (b) Warga mampu
mengakses informasi tentang dampak positif dan negatif pembangkit panas bumi melalui berbagai saluran informasi, media cetak dan online, mesin pencari, media sosial dan interaksi langsung dengan korban lain di lokasi lain di Flores. (c) Proses pembelajaran kolektif sudah dan sedang berlangsung dan sifatnya lintas aktor antara masyarakat adat dan kelompok sosial kritis lainnya. Proses belajar ini telah melahirkan kesadaran kritis dan
transformatif warga terkait ruang hidupnya. Ini yang menjelaskan mengapa warga menolak.
Jadi, merupakan suatu kesimpulan keliru ketika mengatakan bahwa penolakan didasarkan pada masalah “lack of knowledge”. Justru bagi kami, sekali lagi, rumusan ini tidak lain menegaskan beroperasinya pengetahuan akademisi untuk mendelegitimasi pengetahuan
komunitas. warga Poco Leok, lewat siaran pers merespon laporan, Satgas mengatakan tindakan menganggap warga penolak tidak memiliki pengetahuan dan menolak karena
provokasi pihak lain adalah sebuah penghinaan terhadap kemampuan mereka untuk belajar dan mengambil sikap terhadap proyek geotermal.
4. Teknikalisasi masalah: reduksi kegagalan sebagai masalah teknis dan bukan ancaman eksistensial. Dalam laporan Satgas, mengelola kegagalan seperti kasus
Mataloko direduksi hanya sebatas persoalan kegagalan yang bersifat teknis.
Oleh karena itu, model intervensinya yang direkomendasi juga sangat teknis, seperti menyediakan ganti rugi, relokasi, pengadaan genteng untuk menggantikan yang rusak akibat korosi, etc. Tim sebagai representasi negara, cenderung memandang kegagalan itu bersifat superfisial.
Kegagalan hanya sebagai bentuk ekternalitas negatif dari proyek panas bumi yang dapat dikurangi dengan pendekatan teknis.
Padahal penolakan luas terhadap proyek panas bumi sedang menegaskan bagaimana komunitas memandang kegagalan dan keseluruhan proyek panas bumi sebagai ancaman eksitensial terhadap kehidupan. Ini adalah jenis ancaman yang menghancurkan, mematikan, dan meniadakan eksistensi komunitas. Komunikasi ALTER BKGF dengan berbagai pihak menyimpulkan bawa Warga melihat proyek panas bumi telah dan akan menghancurkan (a) ruang adat dan budaya. Di Waesono, Poco Leok, Mataloko dan Atadei, kecemasan ini sangat kuat. (b) proyek PLTP mengubah lanskap nilai berbasis solidaritas
kolektif dengan tatanan nilai berbasis hak individual, pertukaran pasar dan akumulasi kapital.
Dengan akibat merusak tatanan, kesatuan dan kedamaian sosial, karena timbul konflik antar keluarga, antar klan dan antar kampung. Pola-pola pendekatan korporasi yang
memecah belah melahirkan sikap saling curiga, intimidasi dan kekerasan psikologis. (c) Proyek panas bumi juga dilihat sebagai ancaman terhadap sumber daya bersama seperti air, hutan dan lahan pertanian. Ini diungkapkan warga di Wae Sano, Poco Leok, Sokoria dan Atadei. Dalam jangka panjang proyek keamanan energi justru menimbulkan ketidakamanan lain yakni ketidakamanan pangan, ketidakamanan pangan, lingkungan dan
mengancam stabilitas sosial budaya. Bagi warga, proyek gagal di Mataloko memiliki makna ontologis di mana intervensi pembangunan demikian menjadi ancaman serius bagi keutuhan ciptaan dan ruang hidup.
Dengan demikian, kegagalan proyek itu dianggap
sebagai bukti nyata dari dampak geotermal terhadap produksi ruang pengorbanan (sacrifice zone). Ruang pengorbanan adalah ruang yang menampung beban racun, polusi, dan konflik yang disebabkan oleh operasi pembangunan. Ruang ini biasanya dikondisikan oleh latar
struktural yang timpang seperti kuatnya relasi dominasi negara/ kapital terhadap warga.
5. Klaim berlebihan akan teknologi sebagai jalan keluar. Alih-alih mendengarkan tuntutan dan mempelajari secara serius tuntutan warga serta menjadikan itu sebagai agenda
kebijakan, laporan ini malah mempertontonkan kuasa pengetahuan negara melalui klaim intervensi teknologi tinggi. Seolah-olah, persoalan geotermal dilihat semata soal teknis yang dikuasai oleh ahli geotermal semata di mana masalah akan selesai ketika proyek ini akan menggunakan teknologi canggih. Padahal, basis dari penolakan warga bukan semata soal risiko gagal yang disebabkan oleh malpraktik (seperti yang terjadi di Mataloko) tetapi karena pengetahuan dan kesadaran akan ruang berserta lanskapnya.
Pendewaan pada supremasi teknik mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam manajemen risiko karena sesungguhnya kemampuan teknik dan ilmu pengetahuan memiliki keterbatasan dalam mencegah bahaya sebuah kebijakan pada lingkungan dan manusia. Rekomendasi pendekatan teknis oleh tim satgas mengabaikan kegagalan teknis proyek Daratei di Mataloko, ketidakmampuan korporasi dan kapasitas teknisnya untuk mengatasi
semburan uap baru yang makin meluas. ALTER BKGF juga mendapat informasi adanya kegagalan satu sumur di Atadei. Juga adanya kemungkinan dampak pemboran terhadap keretakan tanah di kampung Bo Waru, Jerebuu, Kabupaten Ngada. Di dalam laporan Tim Satgas mengatakan itu terjadi sebelum pemboran, tetapi komunikasi ALTER BKGF dengan warga mengungkapkan keretakan terjadi pasca pemboran.
6. Penggunaan logika ganda privatisasi ruang demi kepentingan publik. Penegasan soal klaim kepentingan publik dan mendorong upaya sertifikasi tanah warga dalam konteks pembangunan geotermal merupakan klaim sekaligus strategi akses dan kontrol atas ruang
hidup warga. Kepentingan publik dan sertifikasi yang menegaskan hak individu seolah terlihat kontradiktif di sini. Namun, secara kritis kita dapat mengatakan bahwa sertifikasi adalah penegasan soal logika privatisasi ruang. Sebuah strategi enclosure (menutup dan
membatasi) akses dan aktivitas lain, misalnya, produksi pertanian dalam jangka panjang dan akses ke sumber daya air. Kondisi ini diciptakan untuk memudahkan akses korporasi terhadap titik-titik geotermal, sehingga pada akhirnya negara dan korporasi dapat mengklaim ruang tersebut atas nama publik. Jadi, penguasaan negara diperoleh dengan cara mengkondisikan proses enclosure. Logika ini bertentangan dengan logika warga dan
gereja yang melihat ruang sebagai the common, yakni ruang bersama yang tidak direduksi
dalam batas legal adminsitratif dan fungsinya melayani dominasi negara. Justru, the common adalah penegasan pemaknaan ruang yang dibangun di atas nalar “politics of belonging” yaitu kemelekatan suatu komunitas sosial atas ruang dan ikatan sosial yang terbentuk di dalamnya.
7. Laporan tim Satgas adalah dokumen politik yang tidak netral. Sangat terlihat jelas dalam laporan ini yang diakomodasi dan diutamakan adalah tujuan-tujuan pemerintah, korporasi, dan juga kelompok pendukung. Dalam dokumen ini, suara dari kelompok pendukung cenderung dirumuskan secara positif dan dianggap memwakili mayoritas kehendak warga. Sebaliknya, tujuan atau objectives dari kelompok yang menolak cendrung
didelegitimasi bahkan dikonstruksi sebagai ancaman dalam mencapai tujuan bersama.
Contoh : dalam laporan terkait Poco Leok, Alih-alih memposisikan warga penolak secara setara dengan warga lain dan memahami penolakan mereka dalam kerangka kewargaan demokratis, laporan ini justru mereproduksi bahasa kekuasaan yang selama ini diproduksi oleh rezim politik di Manggarai untuk mendelegitimasi penolakan warga, seperti memandang penolakan sebagai operasi propaganda politik dan lebih dangkal lagi, demonstrasi warga sebagai ekspresi tuntutan demokrasi direduksi sebagai tindakan pengrusakan barang publik (mengkriminalisasi warga yang dituduh merusak pagar kantor Bupati).
B. Tentang Partisipasi Masyarakat Sipil, Kaum Perempuan Dalam Dan Saat Proses Pembentukan Tim Satgas
1. ALTER BKGF mempertanyakan soal keterlibatan masyarakat sipil baik dalam kerja Satgas dan proses usulan keanggotaan Satgas. Dalam tanggapan terhadap kritik WALHI, Gubernur melalui Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan menyatakan bahwa Satgas dibentuk dengan masukan semua pihak.
2. Realitas menunjukkan bahwa proses perekrutan tidak terbuka sehingga representasi pemangku kepentingan dalam Satgas tidak memadai. Mengingat kompleksitas masalah pembangunan pembangkit geotermal, Satgas seharusnya mereprensentasikan semua pihak yang memiliki keprihatinan terhadap dampak pembangunan proyek geotermal di Flores dan Lembata.
3. Proses pembentukan seharusnya melibatkan representasi memadai dari pemangku kepentingan eksternal yang terkena dampak kebijakan. Organisasi sosial, organisasi lingkungan, NGO yang memiliki perhatian pada isu panas bumi, wakil masyarakat adat terdampak, komunitas di luar lokasi dan komunitas epistemik perlu harus menjadi bagian dari tim Satgas.
4. Komposisi tim berhubungan dengan derajat partisipasi pemangku kepentingan baik yang internal maupun eksternal. Pemangku kepentingan internal adalah mereka yang membuat kebijakan, yang eksternal adalah mereka yang terkena dampak langsung atau tidak langsung dari kebijakan pembangunan pembangkit geotermal.
5. Proses usulan terbuka memungkinkan masyarakat sipil mengusulkan individu-individu dengan keahlian, pengetahuan, kepedulian, independensi, dan pemahaman akan konteks lokal proyek-proyek geotermal di Flores dan Lembata.
6. Proyek geotermal membawa dampak buruk bagi kaum perempuan, terutama kaum Ibu, dan
dalam jangka panjang meningkatkan beban hidup mereka. Kehilangan akses pada tanah
pertanian, sumber mata air, hutan dan lingkungan membuat beban kaum perempuan menjadi lebih berat. Representasi kaum perempuan dalam tim seharusnya menjadi prioritas pembuat kebijakan. Rendahnya partisipasi perempuan dalam tim menunjukkan dominasi
kultur patriaki dalam dan kekurang pedulian pemerintah daerah terhadap kaum perempuan yang terkena dampak pembangunan pembangkit geotermal.
C. Tentang Metode, Waktu dan Kemampuan Menangkap Kegelisahan Sosial
1. Ketidakmampuan tim satgas menangkap esensi persoalan yang diuraikan berhubungan dengan metode rapid appraisal (penilaian cepat) atau uji petik diterapkan. Metode ini sahsah saja untuk menghasilkan pemahaman dan respons cepat terhadap konflik pembangunan pembangkit panas bumi.
2. Pemahaman utuh terhadap persoalan membutuhkan sebuah penilaian yang menggabungkan variasi metode seperti wawancara langsung dengan kelompok masyarakat
yang menolak dan mendukung, kelompok diskusi terarah, studi dokumen dan obeservasi partisipatif di lokasi pembangkit yang menjadi sumber konflik. Dalam laporan ke Sokoria, tim Satgas menyebut tiga metode di atas. Tetapi dengan waktu kunjungan yang sangat
singkat, sementara pihak yang ditemui banyak, sangat sedikit kemungkinan untuk mengkombinasikan metode ini diterapkan. Observasi, misalnya, membutuhkan waktu
cukup untuk memahamai esensi persoalan yang menjadi sumber kegelisahan dan penolakan.
3. Tim Satgas juga perlu menyeimbangkan representasi informan dari kelompok yang mendukung dan yang menolak. Tujuan agar informasi yang diperoleh memadai untuk membuat kesimpulan dan rekomendasi yang seimbang. Berbagai informasi dari warga di lokasi menunjukkan bahwa penilaian hanya dilakukan dua hari, tanpa langsung bertemu dengan warga penolak geotermal. Atau bertemu sangat singkat dengan satu-dua warga
penolak di berbagai lokasi pembangkit dan calon pembangkit geothermal
4. Cara kerja tim dalam mengumpulkan informasi yang cenderung selektif, dengan lebih banyak melibatkan mereka yang mendukung, dilakukan terburu-buru berdampak pada dua hal berikut: pertama, Tim Satgas gagal menangkap esensi persoalan, kegelisahan sosial,
perpecahan dan konflik yang membuat penolakan pada geotermal makin kuat. Kedua, muncul kecurigaan publik bahwa Tim Satgas sebenarnya sudah memiliki kesimpulan yakni proyek geotermal baik dan dilanjutkan. Proses penilaian hanya menjadi instrumen politik dan pengetahuan untuk melegitimasi kebijakan yang telah dibuat.
5. Presentasi hasil kerja Tim Satgas dalam pertemuan tanggal 4 Juli 2025 dilakukan dengan waktu terbatas, terburu-buru dan tanpa perdebatan demokratis. Proses ini hanya memperkuat dugaan publik bahwa bahwa Tim Satgas ini dibentuk tanpa ‘niat baik’ mencari akar persoalan konflik geotermal.
D. Tentang Independensi, Cara Kerja dan Kemampuan Memahami Konteks
1. Independensi adalah isu kunci lain. Tim harus diberi kebebasan untuk melakukan seluruh proses uji petik. Dalam isu kompleks dan politis seperti pembangunan listrik panas bumi, kemerdekaan tim dibutuhkan untuk mampu merumuskan rekomendasi yang obyektif.
Sebuah tim independen, dengan keanggotaan yang tidak terlibat dalam konfik, menjadi sebuah keharusan.
2. Kenyataan bahwa Tim Satgas ‘diawasi’ oleh salah satu pihak yang terlibat dalam permasalahan panas bumi di Flores dan Lembata. Keterlibatan ini jelas menimbulkan
keraguan pada independensi tim dalam memproduksi laporan dan merekomendasikan kebijakan yang tidak bias, tanpa intervensi dan tekanan.
3. Soal profesionalisme tim. Tim Satgas melibatkan akademisi dari universitas-universitas ternama. Latar belakang akademisi sebagai geolog, ahli kimia lingkungan dan kimia organik, ekonomi, kebijakan publik dan sosiologi hanya menunjukkan latar belakang disiplin keilmuan. Persoalannya terletak di sini, masalah panas bumi melibatkan berbagai dimensi politik, sosial, budaya dan ekonomi. Cara kerja tim yang terpisah-pisah, satu orang
untuk satu lokasi menghasilkan pemahaman yang terpenggal-penggal soal masalah panas bumi. Harusnya evaluasi untuk semua titik menggunakan pendekatan multidisipliner dengan anggota tim yang paham konteks sosial, kultural dan lingkungan setempat.
E. Penegasan Posisi ALTER BKGF terhadap hasil laporan Satga geotermal, Transisi Energi dan Proyek PLTP di Flores-Lembata.
ALTER BKGF menyepakati bahwa pengembangan energi terbarukan diperlukan untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan sosial. Karena itu, ALTER BKGF
mendukung upaya pemerintah mendorong produksi dan konsumsi energi terbarukan.
Akan tetapi, ALTER BKGF mendukung dengan berpedoman pada empat kebijakan sikap posisi utama.
Pertama, transisi harus dijalankan dengan memenuhi prinsip keadilan distributif, prosedural, rekognisi dan restoratif. Berdasarkan ketidakadilan yang dirasakan
masyarakat, khususnya dari lokasi-lokasi titik-titik geotermal, ALTER BKGF menolak bukan saja proyek geotermal Flores, tetapi juga hasil evaluasi Tim Satgas karena metode penilaian yang tidak independen/obyektif dan karena itu tidak dapat dijadikan sebagai basis keputusan Gubernur untuk melanjutkan pengembangan pembangkit litrik geotermal.
Kedua, Proses transisi harus mendorong demokrasi energi. Kebijakan transisi harus mendorong kemampuan komunitas memilih, memproduksi, menyimpan dan berbagi jenis energi sesuai dengan sumber daya, kemampuan dan kebutuhan komunitas. Demokrasi
energi memperkuat ikatan sosial melalui jaringan antar komunitas, di mana komunitas dengan sumber energi lebih besar dapat mendukung komunitas lain. Melalui pengelolaan komunal, keuntungan dari penggunaan energi akan langsung dinikmati komunitas. Denganmdemikian, dalam kasus Flores pembangkit panas bumi bukan merupakan pilihan utamamkarena justru menciptakan konsentrasi pengelolaan energi pada korporasi besar, sementara ongkos pembangunannya dipikul oleh komunitas.
Ketiga, mendesak pemerintah menghentikan pembangunan pembangkit panas bumi dan dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk gereja, bekerja sama mengembangkan jenis terbarukan lain yang adil seperti mikro dan mini hidro, tenaga surya berbasis lahan tidak produktif atau listrik rooftop (listrik atap) dan biogas.
Keempat, ALTER BKGF mendesak pemerintah mengalokasikan anggaran publik untuk mengembangkan energi terbarukan di luar panas bumi.
Kelima, Mendesak pemerintah agar kebijakan transisi difokuskan pada pengembangan pencapaian kedaulatan energi. Komunitas, melalui proses pembelajaran bersama,
didampingi dan dilatih oleh pemerintah dan organisasi sosial lain untuk menguasai teknologi, tata kelola produksi dan konsumsi energi yang berbasis pada sumber daya energi non-panas bumi.
Karena dengan cara ini, komunitas memiliki otonomi dan kedaulatan energi dan tidak terus-menerus bergantung pada pihak luar. Keamanan dan ketahanan energi hanya bisa tercapai bila komunitas memiliki otonomi energi dan tidak bergantung terus-menerus pada korporasi dan negara. ***
Tim Aliansi : Koordinator : P. Dr. Felix Baghi, SVD, Ko-Koordinator: Ir. Justin Coupertino, Sekretaris: Josef San Dou (Chicago) Komisi Hukum: Marsellinus Ado Wawo, SH, Vincentius Repu, Komisi Pendidikan & Analisa Data: Wilfridus Leba, RD. Reginaldus Piperno, Komisis Networking & Koalisi: P. Paul Rahmat, SVD (New York), P. Martinus Bhisu, SVD (Paraguay), Rev. Lukas Jua, SVD, Komisi Sosial: Gabriel Goa. *** (WN-01)









