Ketika Titi Jagung Jadi Perlombaan Birokrasi Lembata
Oleh : Richard B. Toulwala, S. Fil., M.Si
(Dosen STPM St. Ursula, Peneliti Kearifan Lokal dan Kebijakan Publik)
WARTA_NUSANTARA.COM : -OPINI– Program Bupati Lembata untuk menjaga kearifan lokal terdengar mulia. Namun, pelaksanaannya melalui perlombaan ‘titi jagung’ khusus untuk ASN justru melahirkan ironi. Alih-alih menghidupkan tradisi, langkah ini justru menampilkannya sebagai mainan hingga tontonan birokrasi yang kehilangan makna. Dalam kaca mata filsafat, ini bukan sekadar keliru, tetapi juga bentuk ketidakmasukakalan politik yang patut dikritik keras.



Kearifan lokal adalah identitas, kekuatan budaya, dan sumber daya sosial yang menopang kehidupan masyarakat. Namun, cara pemerintah daerah Lembata mengekspresikan ‘kecintaannya’ (yang belum tentu benar-benar cinta) terhadap kearifan lokal melalui perlombaan ‘titi jagung’ khusus untuk ASN justru menghadirkan ironi yang menyesakkan. Perlombaan ini lebih menyerupai plesetan yang melemahkan makna kearifan lokal bukan sebaliknya menguatkannya.
Inikah cara kita melestarikan kearifan lokal dengan menjadikannya permainan dan tontonan birokrasi?
Titi Jagung: Tradisi yang Bernapas dalam Hidup Perempuan Desa
Titi jagung bukan sekadar aktivitas teknis. Ia adalah hasil habitus sosial-budaya, seperti kata Pierre Bourdieu, praktik keseharian yang mencerminkan sejarah kolektif dan membentuk identitas perempuan Lembata. Setiap butir jagung yang dititi adalah jejak ketekunan, ekonomi rumah tangga, dan simbol keberlanjutan hidup.


Bagi ibu-ibu di pelosok desa, titi jagung adalah kerja sehari-hari yang menopang keluarga. Di situ ada keringat, ada rasa sakit di telapak tangan, ada kelelahan yang dibayar dengan penghasilan sederhana. Jagung titi dijual, dipasarkan, bahkan menjadi produk khas Lembata.
Kita orang Lembata mengamini jagung bukan sekadar pangan. Ia adalah simbol ketahanan hidup, hasil kerja keras, dan bukti kearifan dalam mengolah alam. Proses titi jagung seperti menumbuk jagung hingga pipih lalu menyangrainya, telah menjadi pekerjaan turun-temurun yang dilakukan, terutama oleh ibu-ibu di pelosok desa dari pagi hingga petang.


Oleh karena itu titi jagung bukan permainan. Ia adalah kerja nyata, rutin, melelahkan, sekaligus bermakna. Dari jagung titi itulah keluarga bisa makan, anak-anak bisa sekolah, dan kehidupan rumah tangga bisa terus berlanjut. Bahkan, jagung titi telah merambah pasar dan menjadi produk khas yang dijual hingga ke luar daerah.
Dengan demikian, titi jagung adalah kearifan hidup. Ia tidak bisa direduksi menjadi sekadar atraksi lomba ASN atau permainan para birokrat. Tapi mengapa ia dipermainkan? ketika pekerjaan sehari-hari ibu-ibu ini dijadikan ajang mainan ASN maka di sinilah kesalahan besar terjadi.
ASN Meniti Jagung: Ironi Habitus dan Alienasi
Ketika ASN dipaksa berlomba meniti jagung, terjadi dua hal sekaligus, yakni pengasingan makna (alienasi) dan kekacauan arena sosial. Dalam kerangka berpikir Karl Marx, kerja ibu-ibu desa yang penuh makna ekonomi dan budaya diubah menjadi tontonan seremonial, sehingga makna asli terasing dari pelakunya. Mereka teralienasi akibat perilaku rakus negara yang merampok panggung mereka. Tak heran, Marx menganggap negara bukan bangunan suci atau bukan lavolente generale, melainkan semata-mata alat eksploitasi kelas yang lebih tinggi terhadap kelas rendah (masyarakat), ya persis yang sedang dipraktekan di Lembata saat ini.


ASN yang semestinya bekerja untuk meningkatkan pelayanan publik kini didorong untuk meniru kerja rakyat kecil. Itu menciptakan distorsi, di mana pekerjaan yang lahir dari kebutuhan hidup masyarakat berubah menjadi hiburan birokrasi. Di sinilah alienasi paling nyata. Rakyat tetap bekerja keras untuk bertahan hidup, sementara birokrat bermain-main dengan pekerjaan itu demi citra politik.
Menempatkan ASN untuk bertanding meniti jagung hanya menghadirkan tontonan aneh. birokrat yang seolah-olah ‘berlomba’ menjadi peniti jagung dadakan. Ini bukan bentuk penghormatan, melainkan reduksi makna. ASN dipaksa meniru pekerjaan masyarakat desa dengan dalih melestarikan kearifan lokal, padahal pada kenyataannya justru menyingkirkan pelaku utama dari panggung utama.
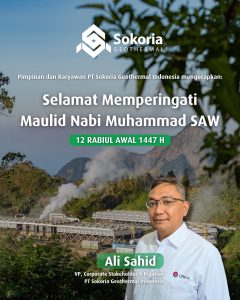
Apakah pemerintah daerah Lembata lupa bahwa yang paling berhak mendapat sorotan adalah ibu-ibu desa yang saban hari berjuang dengan jagung titi?
Relasi Kuasa dan Absurditas Politik di Lembata
Lebih jauh, kekuasaan tidak hanya bekerja melalui kebijakan, tetapi juga melalui simbol dan tubuh, demikian kata Michel Foucault. Perlombaan titi jagung ASN adalah cara kekuasaan menampilkan dirinya. Negara hadir bukan untuk memberdayakan, melainkan untuk menundukkan simbol budaya rakyat ke dalam panggung birokrasi.
Tubuh ASN dipertontonkan sedang meniru kerja ibu-ibu desa. Pesannya jelas, bahwasannya pekerjaan rakyat pun bisa diambil alih oleh negara, dijadikan bagian dari seremonial resmi. Inilah bentuk dominasi halus yang membuat rakyat kecil hanya jadi penonton, sementara penguasa tampil sebagai pemilik panggung.
Perlombaan ini pada akhirnya memperlihatkan absurditas politik lokal. Pertama; ia menciptakan persaingan tidak sehat. ASN seolah-olah bisa ‘menandingi’ ibu-ibu desa dalam meniti jagung. Kedua; ia menampilkan dominasi negara yang berlebihan. Kearifan lokal dipaksa masuk ke dalam arena birokrasi. Ketiga; ia hanya seremonial populis, bukan pemberdayaan.
Bila dilihat dengan kacamata J. P. Sartre, tindakan ini adalah bentuk bad faith (itikad buruk). Berpura-pura peduli pada kearifan lokal, padahal sejatinya hanya untuk kepentingan pencitraan. Titi Jagung oleh ASN yang diperlombakan, didokumentasikan, dan disebarluaskan ke berbagai media sosial adalah pencitraan yang paling hakiki. Dengan kata lain, lomba ini adalah kerja tanpa makna, tindakan politik yang gagal, bahkan sebuah pelecehan terhadap esensi kearifan lokal.
Dari Pemberdayaan ke Pengerdilan
Kearifan lokal bukan untuk dipertontonkan, melainkan diberdayakan. Seharusnya ibu-ibu peniti jagung mendapat dukungan berupa akses pasar, inovasi kemasan, modal usaha, hingga perlindungan hukum atas produk khas mereka. ASN harusnya berperan sebagai fasilitator: mendampingi, memfasilitasi, dan mengangkat pelaku utama. Namun, yang terjadi adalah kebalikannya. Kearifan lokal dikecilkan jadi lomba semu. Ini bukan penghormatan, melainkan pengerdilan.
Lomba titi jagung ASN ini mesti dihentikan. Tidak perlu malu membatalkan surat yang terlanjur memenuhi ruang publik. Bukankah lebih bermanfaat bila ASN dilibatkan untuk membantu promosi produk, menciptakan aplikasi pemasaran digital, atau membangun jalur distribusi jagung titi hingga ke pasar nasional? Mengapa justru mereka dilombakan untuk “meniru” pekerjaan sehari-hari rakyat kecil? Atas nama kesejahteraan (bonum communae), negara ini tidak butuh ASN titi jagung dadakan.
Berhenti Mempermainkan Kearifan Lokal
Perlombaan titi jagung ASN adalah wajah buruk bagaimana kearifan lokal di tanah Lembata dipermainkan atas nama visi politik. Ia mengalienasi makna, mendominasi simbol budaya, dan menciptakan absurditas birokrasi.
Kita harus berani mengatakan dengan lantang: ini bukan bentuk penghormatan, melainkan pelecehan terhadap kearifan lokal.
Pemerintah daerah perlu berhenti menjadikan tradisi sebagai panggung seremonial murahan. Jika serius menjaga kearifan lokal, lakukan lewat kebijakan konkret seperti pemberdayaan, perlindungan, dan dukungan nyata bagi para penjaga tradisi sejati. Para penjaga tradisi adalah para ibu-ibu desa peniti jagung yang saban hari membiarkan wajah ditampar asap api.
Jika pemerintah daerah Lembata benar-benar serius menjaga kearifan lokal, maka pertimbangkan beberapa hal ini. Pertama; pemerintah perlu menyelenggarakan ‘festival jagung titi’ dengan melibatkan ibu-ibu desa sebagai bintang utama. Kedua; pemerintah daerah harus berani menghadirkan program pemberdayaan ekonomi agar jagung titi punya nilai tambah dan daya saing. Ketiga; sudah sepatutnya pemerintah daerah Lembata memberikan perlindungan hukum dan merek dagang agar jagung titi Lembata memiliki identitas kuat di pasar. Keempat; Menugaskan ASN sebagai fasilitator, bukan pemain. Mereka mendampingi, mendukung, dan mengangkat pelaku asli, bukan merebut panggungnya.
Kearifan lokal adalah napas hidup masyarakat, bukan permainan birokrasi. Ia harus ditempatkan dalam ruang yang layak, penuh hormat, dan bermakna. Menyulapnya jadi lomba ASN hanyalah mengkhianati makna terdalamnya. ***







