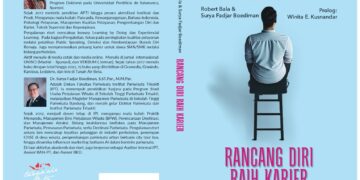Disonansi Politik Indonesia
Oleh : Richard B. Toulwala, S. Fil., M.Si (Dosen Ilmu Politik STPM St. Ursula) & Dr. Anselmus DW Atasoge, S. Fil, M. Th (Dosen STIPAR Ende)
WARTA-NUSANTARA.COM-OPINI– Dalam keseharian masyarakat Indonesia saat ini, ruang digital telah menjadi panggung utama bagi pertunjukan opini politis yang tak terbendung. Media sosial dipenuhi oleh celoteh, sindiran, bahkan caci-maki yang menyasar tokoh publik, institusi negara, dan simbol-simbol kebangsaan. Kita hidup dalam lanskap komunikasi yang saling menelanjangi, namun kebenarannya masih kabur dan perlu diuji secara kritis.


Contoh sederhana bisa disebutkan. Sebuah video potongan pidato tokoh publik yang dipotong tanpa konteks menyebar luas di TikTok dan WhatsApp. Banyak yang langsung percaya dan menyebarkannya. Padahal jika ditonton secara utuh, maknanya sangat berbeda. Di sini, publik tidak hanya menjadi korban, tetapi juga pelaku penyebaran disinformasi.


Ketika informasi diterima tanpa proses verifikasi, yang tersebar bukanlah pengetahuan, melainkan distorsi. Disinformasi dan misinformasi menjadi arus utama yang membentuk persepsi publik. Akibatnya, bangsa ini bisa saja tersesat dalam lembah kekelaman informasi, di mana kebenaran dikaburkan oleh kepentingan, dan pengetahuan digantikan oleh opini yang bias.


Fenomena ini melahirkan pembalikan-pembalikan kebenaran yang sistematis. Kebenaran menjadi relatif, tergantung siapa yang menyuarakan dan untuk kepentingan siapa. Politik berubah menjadi arena saling menyalahkan, saling menjatuhkan, dan saling membakar semangat kebangsaan dengan api kebencian. Etika dan moral publik pun tergerus dan digantikan oleh pragmatisme dan ambisi kekuasaan.


Contoh lain mungkin membuat gagasan ini menjadi makin terang. Seorang guru yang mengajak muridnya berdiskusi tentang nilai-nilai kebangsaan malah dituduh berpihak secara politis karena kutipan yang ia gunakan dari tokoh tertentu. Padahal, niatnya adalah membangun kesadaran kritis. Ini menunjukkan bagaimana ruang pendidikan pun bisa terkontaminasi oleh disonansi politik.


Dalam situasi seperti ini, masyarakat mengalami apa yang disebut Leon Festinger sebagai disonansi kognitif yaitu ketegangan batin akibat benturan antara informasi yang diterima dan nilai yang diyakini. Ketika narasi politik penuh manipulasi, masyarakat cenderung merespons dengan apatisme, skeptisisme, atau bahkan sinisme terhadap politik dan para pemimpinnya. Politik yang seharusnya menjadi seni mengelola kemajemukan demi kebaikan bersama (bonum coomunae), justru dipersepsi sebagai seni merebut kekuasaan dengan segala cara. Dari titik inilah, lahir disonansi politik.
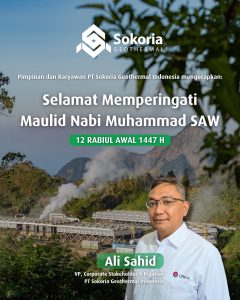
Contoh berikut ini memperjelas ide tersebut. Banyak warga yang memilih tidak ikut dalam musyawarah RT atau forum warga karena merasa “semua sudah diatur dari atas” atau “percuma bicara, toh tidak didengar.” Ini adalah bentuk nyata dari melemahnya partisipasi publik akibat disonansi politik.
Selain partisipasi publik melemah, kepercayan publik kepada pemerintah juga ikut melemah sebagaimana dicontohkan di atas. Ketika rakyat melihat adanya inkonsistensi, legitimasi politik pun melemah. Pada akhirnya, demokrasi bisa kehilangan substansi jika yang menonjol hanyalah perebutan kekuasaan, bukan upaya menghadirkan kesejahteraan dan keadilan.
Di tengah gelombang pembalikan ini, masih ada mereka yang menjaga nurani politiknya. Mereka yang tetap setia pada esensi politik sebagai jalan menuju keadilan dan kesejahteraan bersama. Mereka layak diapresiasi dan dikawal, agar politik tetap berada di jalur yang benar, dan demokrasi Indonesia tidak kehilangan arah.
Jika disonansi politik ini dibiarkan, maka dampak terbesarnya adalah melemahnya partisipasi dan kepercayaan publik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat enggan terlibat, enggan percaya, dan enggan berharap. Tugas kita bersama adalah mengembalikan politik pada martabatnya, dengan membangun narasi yang jernih, etis, dan berpihak pada kebaikan bersama.
Selain itu, tak kalah penting adalah memperkuat konsistensi antara kata dan perbuatan, membangun komunikasi politik yang beradab, serta menumbuhkan budaya politik yang sehat. Tanpa itu, demokrasi hanya akan menjadi ritual prosedural tanpa makna substantif bagi rakyat. ***
Kedua Penulis adalah Richard B. Toulwala, S. Fil., M.Si (Dosen Ilmu Politik STPM St. Ursula) & Dr. Anselmus DW Atasoge, S. Fil, M. Th (Dosen STIPAR Ende)