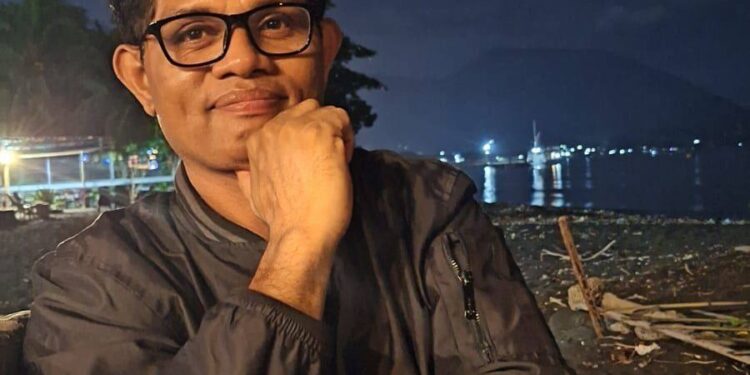Catatan Pertama : Catatan Kritis dari Erich Dalam Tulisan Pertamananya Merespons Kebijakan Pemda Lembata Gelar Lomba
Oleh : Anselmus DW Atasoge
WARTA-NUSANTAA.COM– Tulisan Erich menampilkan gaya retoris yang tajam. Erich secara cerdas memanfaatkan analogi film Office Space sebagai pintu masuk untuk mengkritik birokrasi pemerintah daerah. Satir yang digunakan menghibur, tetapi juga menyentil kesadaran pembaca akan absurditas rutinitas administratif yang kering makna. Kutipan dari Charlie Chaplin dan Hannah Arendt memperkaya dimensi filosofis tulisan ini, memperluas cakrawala pembaca untuk melihat persoalan birokrasi dari sudut pandang eksistensial dan historis.







Kritik terhadap kebijakan juga disampaikan secara kontekstual. Penulis menyoroti lomba Titi Jagung dan Mengetik Cepat sebagai contoh konkret dari kebijakan yang dinilai seremonial dan minim dampak. Keberanian penulis dalam mempertanyakan logika kebijakan tersebut menunjukkan sikap kritis yang dibutuhkan dalam ruang publik demokratis, sekaligus mengajak pembaca untuk tidak menerima kebijakan secara pasif.



Tulisan ini juga menunjukkan kedalaman analisis sosial dan ekonomi. Erich mengangkat ketimpangan antara pelaku ekonomi rakyat, khususnya ibu-ibu petani jagung titi, dan para ASN yang justru dijadikan aktor utama dalam perlombaan yang tidak relevan dengan realitas produksi. Erich juga mengaitkan kritiknya dengan konsep manajemen rantai pasok (supply chain management) dan pentingnya keberpihakan kebijakan terhadap UMKM, sehingga kritik yang disampaikan tidak berhenti pada retorika, tetapi menyentuh akar persoalan struktural.
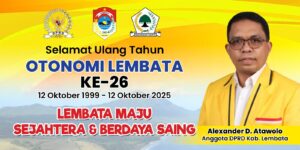


Teori filosofis dari Hannah Arendt tentang labor, work, dan action menjadi fondasi konseptual yang kuat dalam membedah stagnasi birokrasi. Erich tidak hanya mengutip, tetapi juga mengaplikasikan konsep tersebut secara kontekstual. Analogi “tukang vs arsitek” menjadi ilustrasi yang tajam tentang peran ideal pemerintah: bukan sekadar pelaksana rutin, tetapi perancang masa depan yang visioner dan transformatif.



Tulisan ini memiliki kekuatan retoris yang tajam, namun secara struktural cenderung padat dan melebar. Paragraf-paragrafnya panjang dan kadang repetitif, sehingga pembaca bisa kehilangan fokus terhadap gagasan utama. Untuk memperjelas alur dan memperkuat daya analisis, tulisan ini sebaiknya dibagi ke dalam subbagian tematik yang lebih sistematis, seperti: kritik kebijakan Pemda, analisis sosial ekonomi jagung titi, kritik terhadap logika kerja birokrasi, serta solusi dan rekomendasi kebijakan. Pembagian ini akan membantu pembaca memahami arah kritik dan memperjelas posisi penulis terhadap isu yang diangkat.

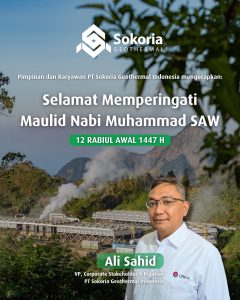
Selain itu, terdapat beberapa pernyataan yang bersifat general dan perlu diperjelas agar tidak menimbulkan kesan hiperbolik atau ofensif. Misalnya, ungkapan “ASN dianggap tak berbeda dengan anak-anak SD” atau “Nasir-Tuaq Tipu” perlu dijelaskan konteks dan maksudnya secara lebih hati-hati. Tanpa penjelasan yang memadai, frasa-frasa tersebut bisa mengaburkan substansi kritik dan mengurangi kredibilitas argumen. Untuk memperkuat klaim, Erich disarankan menggunakan data atau kutipan resmi, seperti jumlah UMKM jagung titi yang aktif, anggaran yang dialokasikan untuk lomba, atau hasil survei kepuasan ASN terhadap program Pemda.


Tulisan ini juga sangat fokus pada kritik, namun belum cukup memberi ruang bagi kemungkinan niat baik di balik kebijakan perlombaan. Padahal, dalam konteks perayaan HUT Otonomi Daerah, perlombaan bisa saja dimaksudkan sebagai sarana edukasi, promosi budaya lokal, atau penguatan solidaritas antar-OPD. Karena itu, Erich perlu menambahkan paragraf yang mengakui potensi positif dari kegiatan tersebut, sembari tetap menekankan bahwa desain dan pelaksanaannya harus diarahkan pada dampak strategis dan berkelanjutan.
Beberapa klaim yang sangat kuat secara naratif, seperti “sistem pasar yang tidak ramah” atau “ibu-ibu tidur di selasar pasar,” akan lebih kokoh jika didukung oleh referensi empiris. Penambahan data dari laporan UMKM, berita lokal, atau hasil observasi lapangan akan memberikan bobot akademik dan memperkuat validitas kritik. Dengan dukungan data, tulisan ini tidak hanya menjadi refleksi kritis, tetapi juga bisa menjadi masukan kebijakan yang konstruktif dan berdampak.
Kedua: Respons terhadap tulisan Erich Wajah Simbolik Jabatan: Bahasa,Kuasa, dan Hermeneutika Kritis Adegan Titi Jagung yang merupakan catatan kritis atas tulisan saya.
1. Kekuatan Argumentatif dan Kedalaman Filosofis
Tulisan Erich menunjukkan kekuatan reflektif yang tinggi. Penulis tidak hanya mengkritisi klaim ADWA, tetapi juga mengajak pembaca untuk memahami hermeneutika secara lebih mendalam, khususnya melalui dua pendekatan Paul Ricoeur:
• Hermeneutika Kepercayaan: Di mana simbol dianggap sebagai wahana pewahyuan makna yang tulus.
• Hermeneutika Kecurigaan: Di mana simbol justru dipandang sebagai kedok yang menyembunyikan kepentingan kekuasaan.
Kritik terhadap ADWA sangat tajam karena menunjukkan bahwa pembacaan simbolik yang terlalu percaya justru berisiko menjadi alat legitimasi kekuasaan.
2. Kritik terhadap Gestur Politik dan Simbolisasi Kekuasaan
Erich berhasil membongkar ‘gestur bupati titi jagung’ sebagai ‘simbol politik yang tidak netral’. Ia menunjukkan bahwa:
• Gestur tersebut bukan sekadar ekspresi budaya, tetapi bagian dari strategi governmentality ala Foucault: seni memerintah melalui citra dan pengelolaan persepsi.
• Simbol politik seperti ini bisa menutupi realitas sosial yang lebih pahit, seperti ketimpangan ekonomi dan penderitaan pelaku ekonomi kecil (ibu-ibu jagung titi).
Ini adalah kritik yang sangat relevan dalam konteks politik lokal, di mana citra sering kali lebih penting daripada substansi kebijakan.
3. Bahasa Kritis dan Kontekstual
• Erich menggunakan bahasa yang tajam, reflektif, dan filosofis, namun tetap komunikatif.
• Referensi terhadap Sapardi Djoko Damono, Paul Ricoeur, dan Michel Foucault memperkuat legitimasi akademik tulisan.
• Kritik terhadap narasi Pemda dan media lokal menunjukkan keberanian intelektual dan kesadaran akan pentingnya ruang publik yang kritis.
4. Catatan
• Keseimbangan Tafsir: Meskipun hermeneutika kecurigaan penting, tulisan Erich cenderung menolak sepenuhnya kemungkinan makna positif dari simbol. Padahal, Ricoeur sendiri tidak menolak hermeneutika kepercayaan, melainkan mengusulkan dialektika antara keduanya.
• Kritik terhadap ADWA bisa lebih dialogis: Alih-alih hanya menolak, penulis bisa mengusulkan cara membaca ulang simbol titi jagung dengan pendekatan yang lebih reflektif dan partisipatif.
• Perlu data empirik: Misalnya, bagaimana dampak nyata lomba titi jagung terhadap pelaku ekonomi lokal? Apakah benar tidak ada perubahan? Kritik akan lebih kuat jika disertai bukti lapangan.
Tulisan ini adalah contoh cemerlang dari praktik hermeneutika kritis dalam ruang publik lokal. Ia mengajak kita untuk tidak larut dalam citra, tetapi berani membongkar makna tersembunyi di balik simbol kekuasaan. Dalam konteks pendidikan politik dan pembentukan warga yang otonom, tulisan ini sangat relevan dan layak dijadikan bahan diskusi lintas bidang.
Sementara tulisan saya sangat sederhana, tanpa membela kepentingan siapa-siapa. Toh, saya BUKAN BAGIAN DARI BIROKRASI di Lembata. Juga bukan ANAK TANAH LEMBATA yang ‘wajib membela’ situasi di Tanah Lembata dengan ‘menikam seluruh jiwa’ untuknya.
Jika boleh, maka izinkanlah saya untuk ‘memberi catatan’ pada tulisan saya yang telah dibedah dengan sangat akademik oleh Erich Langobelen. Berikut catatan saya yang saya beri judul sederhana: Merayakan Simbol, Merawat Makna
1. Penghargaan terhadap Budaya Lokal
Tulisan saya mengangkat titi jagung dari perspektif sosiologis (dari perspektif keilmuan saya pada tataran reflektif) sebagai simbol identitas kolektif masyarakat Lamaholot. Saya hanya coba menunjukkan kepekaan budaya saya dengan menempatkan jagung sebagai “narasi hidup” yang menyatukan warga, bukan sekadar komoditas pangan. Saya memandang ini sebagai bentuk literasi budaya yang sangat penting dalam konteks otonomi daerah.
2. Narasi yang Hangat dan Humanis
Dalam semua tulisan saya, saya berusaha menggunakan gaya penulisan yang komunikatif dan menyentuh. Dengan itu, saya berusaha untuk tidak terjebak dalam jargon birokratis, melainkan menghadirkan narasi yang hidup, hangat, dan membumi. Kalimat seperti “ikut duduk di tikar, ikut memegang tongkol, ikut merasakan denyut kehidupan masyarakat” adalah metafora untuk melukiskan idealisme relasi antara negara dan rakyat. Di titik ini, tidak ada KEPENTINGAN YANG SAYA LAYANI. Justru di sinilah titik star untuk membangun sebuah ‘catatan kritis’ untuk Pemda Lembata dan masyarakat umumnya.
3. Hermeneutika sebagai Jembatan Makna
Dengan menyebut “titik hermeneutiknya”, saya hendak menunjukkan bahwa saya tidak sekadar mendeskripsikan peristiwa, tetapi juga MENGAJAK PEMBACA UNTUK MENAFSIRKAN MAKNA DI BALIK SIMBOL. Ini adalah pendekatan yang reflektif dan filosofis, sekaligus membumi. Dari perspektif Erich, hermeneutika dalam tulisan ini tidak elitis. Dan, memang saya tidak mau masuk ke wilayah itu. Yang mau saya tunjukkan adalah hal yang sangat sederhana, yakni hermeneutika sebagai ‘alat untuk memahami kehidupan sehari-hari masyarakat’. Saya berangkat dari titik yang sangat sederhana. Namun, Erich berhasil ‘membuatnya menjadi yang sangat luar biasa’. Salut dan hormat terhadap keluar-biasaan akademik Erich.
4. Pembangunan sebagai Proses Sosial
Sederhananya, tulisan saya hendak menggeser paradigma pembangunan dari sekadar infrastruktur menuju relasi sosial dan kultural. Dalam tulisan saya, saya menegaskan bahwa pembangunan yang bermakna adalah yang menyentuh rasa, bukan hanya angka. INI ADALAH KRITIK HALUS NAMUN KUAT TERHADAP MODEL PEMBANGUNAN YANG TERLALU TEKNOKRATIS DAN JAUH DARI RAKYAT. Sekali lagi, di titik inilah, pertanyaan Erich tentang siapa yang saya layani, mungkin bisa terjawab. Tentu, dengan sedikit menunduk dan mengatup jemari di dada.
5. Kohesi Sosial sebagai Inti Otonomi
Dengan menyoroti interaksi antara ASN dan warga dalam lomba titi jagung, secara sederhana pula saya hendak menunjukkan bahwa OTONOMI DAERAH BUKAN HANYA TENTANG DESENTRALISASI KEKUASAAN, TETAPI TENTANG KEDEKATAN EMOSIONAL DAN SOSIAL ANTARA PEMERINTAH DAN RAKYAT. Dan, di titik ini pulalah terkandung KRITIK RINGAN terhadap Pemda Lembata. Ya…Boleh dipandang juga sebagai pelajaran penting bagi banyak daerah lain di Indonesia.
Menyulam Tradisi dan Pemerintahan
Ya…sekali lagi sederhananya, tulisan saya tersebut merupakan sebuah ‘jurnalisme reflektif yang menggabungkan narasi budaya, semangat lokal, dan pemikiran filosofis’ dengan cara yang amat sederhana dan mungkin jauh dari ranah akademis. Saya hanya coba mengabarkan peristiwa dan menghidupkan makna. Dan, itulah gaya dan daya saya dalam menulis sebagai ‘bagian yang tak terpisahkan dari kerja diam jurnalisme saya’.
Namun, tak apalah. Catatan kritis Erich ‘membuka kesadaran’ saya bahwa tidak serampangan saja menulis di media massa. Butuh kuriositas yang mendalam. Mungkin di suatu saat nanti saya bisa memenuhi harapan Erich. Tentu tidak di media massa, tetapi di media yang lebih akademik! ***
Wajah Simbolik Jabatan: Bahasa,Kuasa, dan Hermeneutika Kritis Adegan Titi Jagung
Oleh : Gregorius Duli Langobelen
(Direktur Eksekutif Tenapulo Research)

“Kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan absolut korup secara absolut.” –Lord Acton
Beberapa waktu terakhir ramai dibicarakan tentang perlombaan Titi Jagung dan Mengetik Cepat bagi para ASN antar OPD untuk menyongsong HUT Otonomi Daerah ke-26 Kab. Lembata. Saya sendiri telah memberi catatan kritisnya dalam artikel berjudul “Office Space, Logika Minimalis Pemda dan Rapuhnya Birokrasi Kita”
Catatan kali ini adalah kelanjutannya yang ditujukan untuk dua hal: pertama, merespon tulisan Pak Anselmus Dore Woho Atasoge (ADWA) berjudul “Hermeneutik ‘Titi Jagung’ dan Wajah Otonomi yang Membumi”; dan kedua, membaca bahasa dan wajah simbolik jabatan seorang bupati ketika melakukan adegan Titi Jagung.
Panggilan Filosofis Menuju Hermeneutika Kritis
Saya sepakat ketika ADWA dalam artikelnya menerangkan “bahwa titi jagung merupakan ‘cerminan cara hidup masyarakat agraris yang menjunjung tinggi kerjasama dan kebersamaan’. Ketika otonomi daerah memberi ruang bagi budaya lokal untuk tampil, masyarakat merasa dihargai bentuk ruang sosial yang memperkuat ikatan antar individu.” Namun, selebihnya saya menolak, atau sekurang-kurangnya mencurigai bahwa ADWA dalam klaim-klaim selanjutnya hanya bermain pada pembacaan periferal, berhenti pada lapisan paling luar dari banyaknya kedok sebuah peristiwa simbolis.
Klaim bahwa Lomba Titi Jagung antar OPD “menunjukkan bahwa birokrasi bisa menyatu dengan budaya masyarakat pada umumnya [dan] memperlihatkan wajah otonomi daerah yang membumi, [dan] di situlah titik hermeneutikanya. [dimana] Pemerintah hadir bukan sebagai pengatur dari atas, tetapi sebagai mitra.. [dan] Solidaritas tumbuh…” adalah klaim epestemik yang terburu-buru, lemah, dan dangkal, karenanya bermasalah. Kenapa demikian? Untuk menjawabnya kita mesti paham apa itu hermeneutika.
Hermeneutika sepintas adalah ilmu atau seni penafsiran dan pemahaman terhadap teks, entah sebagai tulisan, lisan, maupun perbuatan. Tapi, sebenarnya tidak sesederhana itu. Menyederhanakan hermeneutika hanya sebagai tafsir umum adalah persoalan filosofis yang mesti dibedah. Dan itulah yang terjadi pada tulisan ADWA, dimana kerangka hermeneutiknya hanya berhenti pada apa yang disebut oleh Paul Ricoeur sebagai hermeneutika pemulihan makna atau hermeneutics of faith (Ruthellen Josselson: 2004). Pendekatan ini beroperasi dengan landasan “kepercayaan” [penuh] terhadap teks, simbol, atau gestur yang diinterpretasikan, dengan asumsi dasar bahwa simbol adalah wahana pewahyuan kebenaran atau niat baik. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa pembuat kebijakan juga partisipan adalah ahli atas pengalamannya sendiri dan mampu serta bersedia untuk membagikan makna yang tulus. Tapi sekali lagi di situlah soalnya.
Ansel lupa bahkan abai pada realitas dunia birokratis sebagai ruang politis yang selalu penuh dengan kedok/topeng, intrik, dan segala gestur manipulatif kekuasaan. Pejabat politik, meminjam frasanya Sapardi Djoko Damono, seringkali “bilang begini, maksudnya begitu.” Bahkan dalam banyak cara, ASN pada struktur paling kecil hanyalah petugas fungsional atau objek pelaksana lain dari kepentingan politik kekuasaan tertentu. Akibatnya, alih-alih mengungkap maksud dari sebuah keputusan politis, penafsiran yang dihasilkan oleh ADWA justru tidak melibatkan pertimbangan kritis, sehingga berdampak sebaliknya, yaitu melegitimasi kebijakan yang keliru serta menegaskan citra yang bisa saja diam-diam ingin diproyeksikan penguasa.
Tidak heran, narasi tentang kebutuhan jaminan fasilitas, regulasi rantai pasok, sistem pasar yang berkeadilan, serta visi yang berorientasi pada kelompok rentan, seperti pedagang kecil, terutama Ibu-Ibu pelaku ekonomi jagung titi semakin tenggelam. Ibu-ibu yang sama akan tetap terpaksa menginap di emperan toko, supaya jagung titi-nya lebih mungkin laku terjual, di tengah rendahnya harga dan permintaan merosot. Mereka bukan pejabat eksekutif, mereka juga bukan anggota parlemen yang bukan hanya punya gaji tetap, tetapi juga tunjangan selangit.
Untuk memperbaiki ketidakkritisan ADWA, kita bisa merujuk pada Paul Ricoeur ketika memperkenalkan hermeneutika kecurigaan (hermeneutics of suspicion). Jika hermeneutika kepercayaan dianimasikan oleh kepercayaan, maka hermeneutika kecurigaan digerakkan oleh skeptisisme dan ketidakpercayaan. Sikap fundamentalnya adalah mendekati teks, simbol, gestur atau produk kebijakan politik tertentu bukan sebagai wahana kebenaran, melainkan sebagai sebuah “penyamaran” (disguise) yang menyembunyikan atau mendistorsi makna lain yang lebih fundamental. (Paul Ricoeur:2022).
Tujuan dari hermeneutika kecurigaan ini bukanlah memulihkan makna pada permukaan (kedok/topeng), melainkan “membongkar” makna yang tersembunyi di baliknya. Kecurigaan ini secara sistematis diarahkan pada “kebohongan dan ilusi kesadaran” dengan asumsi utama bahwa apa yang tampak di permukaan seringkali merupakan manifestasi dari dinamika yang tidak disadari atau sengaja disembunyikan oleh konflik kepentingan kelas, kehendak untuk berkuasa, termasuk pemanfaatan rasa pasrah atau tunduk dari bawahan kepada atasan.
Demikianlah saya meyakini bahwa memilih untuk “percaya” pada citra yang disajikan oleh kekuasaan adalah bentuk kepatuhan epistemik, jauh sikap para pencari kebenaran (kuriositas). Sebaliknya, memilih untuk “curiga” adalah langkah pertama menuju pengetahuan, menuju kewargaan yang kritis dan otonom. Karena itu, kecurigaan dalam konteks ini bukanlah sinisme tak berdasar, melainkan sebuah metode analitik-sistematik untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang seringkali tak muncul pada ruang publik, misalnya: “Kepentingan siapa yang dilayani oleh penafsiran ADWA ini? Perspektif siapa yang dikesampingkan atau terancam dibungkam?”
Bupati Titi Jagung: Bahasa, Kuasa, dan Wajah Simbolik
Dalam menganalisis wacana politik, hermeneutika kecurigaan bukan lagi sekadar opsi metodologis. Lebih dari itu, merupakan imperatif etis. Sebab, wacana politik secara inheren adalah arena dimana kekuasaan bekerja melalui bahasa untuk membentuk persepsi, memanipulasi kebenaran, menaturalisasi ideologi, dan mengamankan monopoli/dominasi. Dalam kesadaran yang demikian, percaya begitu saja pada gestur politis bupati, seperti pada adegan foto titi jagung, atau juga menerima begitu saja narasi super positif (propaganda?) dari release berita Pemda yang disebar di banyak media online lokal adalah sikap yang secara tidak langsung berpartisipasi dalam pelanggengan ilusi yang diciptakan oleh kekuasaan. Lagi-lagi pertanyaanya, kenapa demikian?
Ingat! Gestur seorang pejabat publik, terutama bupati, yang meniru aktivitas rakyat kecil, misalnya titi jagung, tidak bisa ditafsirkan secara harfiah sebagai tanda “otonomi yang membumi” atau sebagai sebuah bukti otentik kedekatan seorang pemimpin dengan akar rumput. Cara seperti itu merupakan praktik lain dari “hermeneutika dangkal” yang hanya berhenti pada kulit, pada topeng/kedok. Jika sikap ini tidak segera dibongkar, maka kita selamanya akan gagal mengenali bahwa dalam arena politik, bahasa dan gestur bukanlah medium komunikasi yang transparan, melainkan instrumen kekuasaan yang bekerja secara halus untuk membentuk persepsi dan melanggengkan hegemoni melalui simbol-simbol.
Di sini, simbol berbeda dari sekadar tanda. Tanda memberikan informasi yang jelas dan langsung, seperti rambu lalu lintas yang memberikan arah. Tapi, simbol bisa memiliki lapisan makna yang lebih dalam, tidak selalu tunggal, dan seringkali bertentangan. Simbol berperan ganda: ia mengungkapkan sesuatu, tapi pada saat yang sama menyembunyikannya. Dalam konteks itu, adegan bupati “titi jagung” adalah simbol yang menyembunyikan fakta lain yang bertentangan dengan narasi dari Pemda sendiri.
Artinya, sudah sangat mungkin adegan bupati titi jagung bukan mutlak sebagai tindakan solidaritas yang tulus sebagaimana yang kelihatan, melainkan sebuah siasat pemaknaan yang licik untuk tujuan-tujuan yang politis tersembunyi. Lebih dari itu, ia memproduksi dan menaturalisasi mitos tentang “pemimpin yang merakyat”, mirip drama Mulyono ketika masuk gorong-gorong, tapi pada gilirannya berfungsi untuk menyembunyikan dan melanggengkan hubungan kekuasaan sebuah rezim tertentu.
Dalam bahasanya Michel Foucault, tindakan politis Bupati di atas disebut sebagai governmentality, yaitu “seni memerintah” yang melampaui aparatus negara dan tidak beroperasi melalui kekerasan atau hukum semata. Ia adalah serangkaian taktik, prosedur, dan rasionalitas yang bertujuan untuk mengelola dan mengarahkan perilaku, keinginan, imajinasi, dan keyakinan banyak orang demi mencapai tujuan-tujuan tertentu (Abdil: 2024). Adegan bupati titi jagung, dengan demikian, adalah praktik governmentality yang par excellence. Ia tidak memaksa warga untuk patuh melalui ancaman, melainkan membentuk citra dan persepsi mereka secara halus. Orang lewoleba bilang main halus: bekerja dari dalam, melalui produksi hasrat dan identifikasi emosional. Warga merasa membuat pilihan yang otonom, padahal preferensi dan pilihan mereka telah diskenariokan dan diarahkan oleh kekuasaan itu sendiri.
Akhirnya, dapat ditegaskan kembali bahwa dalam ranah politik, tidak ada adegan yang murni netral. Setiap citra, setiap gestur, dan setiap kata adalah medan pertempuran di mana makna dinegosiasikan, ideologi disebarkan, dan kekuasaan dilanggengkan atau ditantang. Demikianlah, gestur “membumi” atau adegan titi jagung pejabat, termasuk bupati, bukanlah sekadar representasi dari karakter, melainkan produksi aktif dari sebuah persona yang dirancang untuk membangkitkan popularitas, tapi serentak menonaktifkan kritik. ***