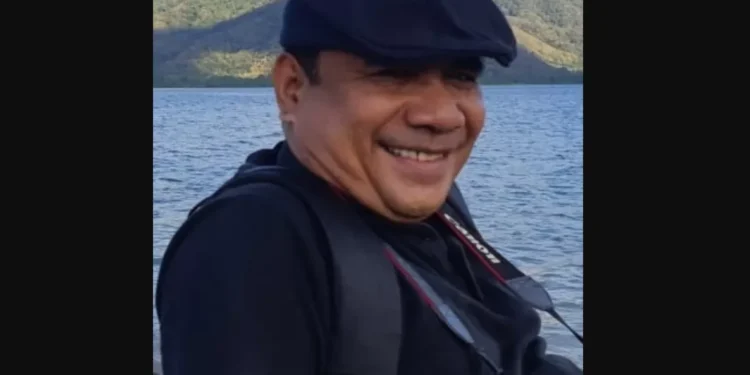Upaya Suap Rp 150 Juta dan Tindakan Polres Nagekeo Menolak Laporan PMKRI
Oleh : Steph Tupeng Witin

Pimpinan demo turun dari mobil dan menyampaikan niat baik mereka kepada polisi yang berdiri di depan gerbang Polres. Mahasiwa tidak diizinkan masuk tanpa alasan. “Pokoknya, tidak boleh masuk!”. Ada ketakutan di balik badan yang tegap, wajah sangar sambil menenteng senjata. Padahal, mahasiswa datang tanpa amarah, tanpa batu, tanpa niat ricuh, hanya suara lirih dari pengeras suara bertenaga aki dan setumpuk bukti dugaan kejahatan yang melibatkan oknum aparat.
Namun institusi yang seharusnya melindungi justru menolak membuka pintu. Lebih absurd lagi, sebelum aksi berlangsung, mahasiswa ditawari suap Rp150 juta agar membatalkan demo. Upaya itu bukan sekadar pelecehan moral, melainkan alarm keras bahwa ada sesuatu yang sangat ingin disembunyikan di balik pagar Polres. Kita menduga, Polres Nagekeo masih sangat kuat dicengkeram ketiak mafia waduk Lambo. Mungkin juga ada “bekingan” dari orang kuat yang semakin ke sini semakin memberi informasi ternyata orang yang dipuja dan disembah gerombolan mafia melebihi “tuhan” itu sangat lemah. Kalau orang kuat saja tampak panik dan ketakutan, apalagi para kecoak mafia yang hanya “mengais” tinja seputar ketiak. Maka kita bisa membaca argumentasi dan jalan pikiran para peneror yang ugal-ugalan, liar dan tidak terkendali akal sehat. Tidak penting substansi, asalkan suara besar bernada teror, bisa serang pribadi, tebarkan hoaks dan kebohongan secara berulangkali di media sosialnya dan yang tidak kalah abrudnya: yang penting penampilan berdasi saat duduk di tempat yang sepintas tampak dari jauh mirip toilet.
Mahasiswa tidak datang membawa rumor. Mereka membawa laporan yang memuat dugaan kuat mengenai keterlibatan oknum polisi dalam mafia tanah Waduk Lambo/Mbay, bisnis galian C ilegal, penyelundupan hewan antardaerah, penyimpangan BBM bersubsidi, dan kasus kematian empat pekerja seks serta satu anggota polisi di Coklat Café. Semua ini bukan cerita pinggiran, melainkan isu yang telah lama dikeluhkan warga, pastor, pengacara publik, dan kelompok masyarakat sipil. Laporan itu seharusnya diterima, dipelajari, dan ditindaklanjuti. Namun Polres menutup pintu, seolah-olah laporan itu bom waktu yang tidak boleh meledak di dalam ruangan mereka.
Menurut hukum, Polri tidak punya pilihan selain menerima laporan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Perkapolri Nomor 7 Tahun 2022, hingga PP Nomor 2 Tahun 2003 dengan tegas melarang polisi menolak laporan masyarakat. Menolak laporan bukan hanya tindakan yang melanggar prosedur, tetapi juga pelanggaran etik yang dapat berujung sanksi disiplin berat. Ketika Polres Nagekeo memilih menutup gerbang dan menolak berkas mahasiswa, mereka tidak hanya mengabaikan undang-undang; mereka mengkhianati mandat dasar Polri sebagai pelindung dan pelayan masyarakat.
Karena itu, apa yang terjadi di depan gerbang Polres bukan sekadar insiden kecil di daerah terpencil. Ini adalah gambaran paling telanjang tentang bagaimana jaringan mafia dapat beroperasi nyaman ketika institusi negara tidak lagi berdiri bersama rakyat. Sikap Polres Nagekeo bukan sekadar defensif; ia mencerminkan ketakutan. Ketakutan pada laporan. Ketakutan pada bukti. Ketakutan pada mahasiswa yang tidak bisa dibeli. Dan dalam ketakutan itulah publik akhirnya melihat sesuatu yang selama ini samar: bahwa persoalan mafia di Nagekeo bukan hanya soal kejahatan di luar institusi, tetapi persoalan dalam institusi itu sendiri. Polres Nagekeo kita duga kuat sedang menyembunyikan otak mafia waduk Lambo yang berdasarkan data dan fakta lapangan: diduga sangat kuat terlibat dalam banyak kasus kejahtaan yang harus diselidiki institusi polisi. Memang banyak sesama gerombolan mafia yang memujanya dalam media abal-abal tetapi publik Nagekeo tersenyum geli karena semua itu terkait dengan kafe coklat dan orang-orang yang berada dalam cangkang mafia.
Siang itu, bukan hanya gerbang besi Polres yang ditutup rapat, tetapi juga barisan aparat berseragam lengkap, berjajar seolah menghadapi ancaman nasional. Ada perbedaan yang mencolok antara dua dunia yang berhadapan hari itu: dunia kekuasaan yang bersenjata, didanai penuh negara, dan dilindungi oleh institusi, dan dunia moralitas mahasiswa yang hanya membawa keberanian, nurani, dan pengeras suara yang sesekali mati karena aki melemah. Anak-anak muda idealis ini hadir dengan moralitas kesederhanaan untuk menyampaikan aspirasi publik sebagai pantulan dari realitas Nagekeo yang sedang dihancurkan gerombolan mafia dan diduga kuat didukung oleh orang lemah Jakarta. Orang lemah membekingi orang lemah dengan memanfaatkan sepotong kuasa negara yang dibiayai uang rakyat. Tindakan ini sangat tidak beradab karena menyalahgunakan kuasa sepotong itu dengan biadab. Kebiadaban itu merembes masuk ke otak para peneror dan pendengung mafia yang bersahut-sahutan menyerang pribadi semua orang yang bekerja tulus dan berjuang dengan nurani untuk membongkar jejaring mafia keparat. Ketika gerombolan mafia peneror dan pendengung kehilangan kewarasan dalam berperilaku, mereka tampak blingsatan seperti ulat kepanasan di atas jalan beraspal dekat Nangaroro.
Moralitas dan Ketakutan
Ada hal yang sangat menggelitik: mengapa Polres Nagekeo tampak begitu takut pada mahasiswa yang bahkan tidak mencapai dua lusin orang? Apa yang membuat suara mahasiswa-yang mengandalkan sound system seadanya-lebih menggetarkan daripada pengeras suara canggih di acara seremonial Polri? Jawabannya terletak pada satu kata: kebenaran.
Kebenaran selalu mengancam struktur yang rapuh. Dan semakin besar kekuasaan menutup diri dari kebenaran, semakin besar pula ketakutan yang ditimbulkannya. Di Nagekeo, kebenaran itu adalah adanya dugaan keterlibatan oknum-oknum aparat dalam jaringan mafia yang merajalela: mafia tanah Waduk Lambo/Mbay, mafia galian C ilegal, mafia penyelundupan hewan, mafia BBM bersubsidi, dan mafia prostitusi yang pernah memakan korban empat pekerja seks serta satu anggota polisi.
Ketika jaringan mafia telah bekerja bertahun-tahun dan diduga memiliki perlindungan dari oknum aparat polisi dan oknum aparat polisi yang bergitu leluasa melakukan dugaan kejahatan karena diduga dibekingi orang lemah Jakarta, keberanian belasan mahasiswa bukan sekadar aksi. Itu adalah ancaman eksistensial bagi bangunan gelap yang dibangun dengan uang, intimidasi, dan pembiaran struktural. Bangunan gelap mafia itu biasanya bersuara besar hanya untuk meneror, mengancam dan seringkali menjual nama orang lemah dari Jakarta dan sekitarnya hanya untuk menarasikan kelemahan psikisnya dan kesakitan jiwa bekingannya.
Upaya Suap Rp150 Juta: Bahasa Ketakutan
Tidak ada kejahatan besar yang berjalan mulus tanpa uang. Dan tidak ada jaringan mafia yang bertahan lama tanpa suap. Suap sudah menjadi “credo” para mafia dan celakanya, suap itu yang hendak diajarkan kepada para mahasiswa, masa depan bangsa. Sebelum aksi mahasiswa berlangsung, seseorang-yang diduga perantara oknum aparat-menghubungi mahasiswa PMKRI lewat telepon seluler dan menawarkan suap Rp150 juta agar aksi dibatalkan. Mahasiwa menolak. Perjuangan membela rakyat yang menderita dan menjaga hati nurani jauh lebih berharga daripada uang haram. Penolakan itu kita pastikan membuat para mafia dilanda kepanikan dahsyat karena otak mafia selalu berpikir bahwa uang itu segala-galanya. Uang bisa membeli integritas seperti orang lemah dari Jakarta.
Suap ini bukan hanya sebuah transaksi. Ia adalah cermin ketakutan. Tidak ada orang yang percaya diri menawarkan uang sebesar itu hanya untuk menghentikan demonstrasi kecil yang bahkan tidak mampu menghasilkan suara orasi yang stabil karena sound system hanya ditopang aki
Uang suap Rp150 juta adalah “uang tutup mulut”. Tetapi juga “uang pengakuan”. Dengan menawarkan suap, mereka mengakui bahwa kritik mahasiswa benar, bahwa laporan mahasiswa mengandung risiko, bahwa suara publik bisa mengguncang kekuasaan, bahwa serial tulisan yang membuka tabir dugaan praktik mafia di Nagekeo menghadirkan bandang kepanikan dan bahwa ada sesuatu yang mereka upayakan agar tetap tersembunyi. Mafia memang selalu doyan membungkam suara kiritis yang melawan kebohongan yang mereka ulangi terus menerus tapi tidak sanggup melumpuhkan nalar kritis rakyat. Rakyat Nagekeo, tanpa ajakan untuk mempercayai narasi kebenaran pun sudah mampu memetakan suara mafia peneror dan pendengung dari suara hati jernih yang membela rakyat Rendu yang hendak dirampok hak-haknya oleh gerombolan mafia. Andaikan gerombolan mafia ini manusia normal dan waras, urat malunya pasti memerah dan memanas. Tapi dasar mafia, ketika anak panas narasi kebenaran menghujam dada, para pembohong ini kelimpungan, panik dan kehilangan akal sehat. Lalu menerjang tak karuan, membabi buta.
Ketika mahasiswa menolak uang itu, struktur kekuasaan gelap mulai retak. Moralitas adalah sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan. Kita patut memberikan apresiasi pada para mahasiswa PMKRI yang ketat menjaga integritas sejak muda. Ketahanan aktivis PMKRI menolak godaan biadab para mafia melalui uang suap itu ibarat anak panah yang melesat dari nurani mereka menghujam jantung gerombolan mafia dan pembekingnya.
Dalam studi sosiologi kekuasaan, situasi seperti di Nagekeo menggambarkan fenomena moral panic, ketika institusi yang selama ini merasa kuat tiba-tiba berhadapan dengan wilayah yang tidak bisa dikontrol: suara moral. Mahasiswa tidak bisa diancam dengan rotasi jabatan. Mereka tidak bisa dibeli dengan proyek. Mahasiwa tidak bisa diatur dengan relasi feodal. Mahasiswa tidak bisa diteror oleh Serfolus Tegu dengan menjadikan Polres Nagekeo sebagai tameng kejahatan. Mahasiswa juga tidak lagi menaruh hormat kepada para (mantan) orang kuat yang dalam kasus mafia waduk Lambo telah bertransformais menjadi orang paling lemah di muka bumi ini. Para aktivis PMKRI itu tidak punya kepentingan lain selain kebenaran. Itulah yang membuat mereka berbahaya. Dan itu yang melumpuhkan kebiadaban teror dan serangan liar para mafia keparat.
Dalam sejarah mana pun, dari mahasiswa Mei 1998 hingga mahasiswa dalam Arab Spring, penguasa yang bekerja dengan pola kekuasaan gelap selalu gentar pada mahasiswa. Mahasiswa adalah “aktor yang belum terdistraksi kepentingan”, sesuatu yang jarang dimiliki pejabat atau pelaku ekonomi. Dan itulah sebabnya Polres Nagekeo menutup pintu. Karena jika pintu dibuka, suara itu akan masuk. Dan jika suara masuk, benteng yang dibangun bertahun-tahun dari uang gelap, kolaborasi gelap, dan jaringan gelap akan runtuh.
Melanggar Hukum
Mari kita letakkan fakta hukum secara lugas: polisi tidak punya hak untuk menolak laporan masyarakat. Titik. Dalam hukum Indonesia, tidak ada pasal, ayat, pedoman, SOP, atau alibi apa pun yang dapat membenarkan penolakan laporan publik.
UU No. 2/2002 tentang Kepolisian menegaskan bahwa polisi wajib menerima laporan dan pengaduan. Peraturan Kepolisian RI Nomor 7 Tahun 2022 mempertegas larangan bagi polisi untuk menolak laporan. Peraturan Polri Nomor 6 Tahun 2019 menjelaskan bahwa siapa pun-baik korban langsung maupun saksi-berhak membuat laporan. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 serta Peraturan Polri Nomor 14 Tahun 2011 menetapkan bahwa menolak laporan adalah pelanggaran disiplin dan kode etik berat. Ini pelanggaran hukum.
Ketika Polres Nagekeo menolak laporan mahasiswa PMKRI, mereka tidak sekadar tidak profesional. Mereka melanggar undang-undang. Mereka melanggar sumpah jabatan. Mereka melanggar aturan internal. Mereka melanggar mandat konstitusional. Dan mereka mengkhianati rakyat yang membayar gaji mereka melalui pajak.
Seandainya peristiwa ini terjadi di negara demokrasi yang matang, seperti Jepang, Jerman, atau Korea Selatan, Kapolres sudah mundur, Kabag Ops sudah diperiksa, anggota Polres yang terlibat sudah dibekukan, dan penyelidikan internal sudah dimulai bahkan sebelum media menurunkan headline. Kalau di Polres Nagekeo, oknum polisi yang diduga kuat menjadi otak mafia justru dirawat, menjadi oknum piaraan orang lemah dari luar Nagekeo dan menggunakan pengacara mafia berdasi untuk menebar teror, hoaks dan kebohongan bersahut-sahutan seperti gerombolan kecoak yang mendesah bersahutan di dinding bangunan lapuk. Bahkan institusi polisi di atasnya bisa mendesain sandiwara hukum yang kita duga dibekingi orang lemah yang doyan mengubah warna kulitnya sesuai konteks realitas yang hendak dirampok. Persis bunglon.
Dalam etika pelayanan publik modern, polisi bukanlah penguasa, bukan pemilik wilayah, bukan tuhan kecil di daerah. Mereka hanya pelayan publik. Mereka menerima gaji dari uang rakyat. Mereka menggunakan kendaraan yang dibeli dari APBN. Mereka menempati gedung yang dibangun dengan dana publik. Ketika mereka menutup pintu Polres dan menolak laporan rakyat, mereka sedang mengatakan bahwa Polres bukan milik rakyat, tetapi milik mereka. Ini adalah bentuk paling parah dari arogansi institusional.
Romo Franz Magnis-Suseno menulis dengan sangat tepat: “Negara kehilangan moralnya ketika menolak mendengar suara yang lemah.” Polres Nagekeo bukan hanya menolak suara yang lemah. Mereka bahkan mencoba membungkamnya dengan segala cara. Dan di titik itu, moralitas polisi runtuh. Bahkan pensiunan yang masih bernafas berusaha mengabadikan jejak kuasanya dengan membekingi oknum aparat polisi yang memang lemah dan sakit jiwa agar bisa dikendalikan seperti robot berwajah polisi. Ketika robot polisi bergerak ke bibir waduk Lambo, berhamburan gerombolan mafia: pengacara murahan, aparat kelas teri, wartaan KH Destroyer dan tuan tanah palsu alias tuan tanah dadakan. Mereka semua kelaparan berebut tinja di ketiak pensiunan. Siapa yang menghambat pemenuhan hasratnya pasti diterjang, diteror dan dikriminalisasi. Pola itu menjadi “habit” para mafia yang dididik orang lemah dari luar Nagekeo. Publik menikmati tarian kebohongan gerombolan mafia yang bila dilawan pasti memuntahkan tinjanya berderet-deret di dalam got berbau.
Jika Polres menolak laporan karena alasan keamanan, itu bisa dipahami. Jika Polres menolak laporan karena belum ada waktu, itu masih bisa didiskusikan. Tetapi menolak laporan disertai upaya suap bukanlah tindakan institusional. Itu adalah tindakan “perorangan dengan kekuasaan”. Artinya, polisi yang menolak laporan mahasiswa bukan sedang melindungi institusi Polri. Mereka melindungi kepentingan tertentu yang terancam oleh laporan itu. Kepentingan ini bisa berupa jaringan mafia, hubungan personal, aliran uang, jabatan atau rahasia yang tidak boleh diketahui publik.
Yang jelas bukan kepentingan rakyat. Karena jika kepentingan rakyat adalah prioritas, gerbang Polres pasti dibuka, laporan pasti diterima, dan mahasiswa pasti disambut. Karena rakyatlah yang membiayai Polres, bukan mafia.
Tersandera Kepentingan Gelap
Fenomena yang terjadi di Nagekeo sejatinya bukan hal baru dalam kajian tata kelola dan sosiologi negara. Ilmu politik mengenal istilah institutional capture, institusi negara yang ditangkap oleh kepentingan privat, sehingga berhenti menjalankan fungsi publiknya.
Kejahatan terorganisir di berbagai negara menunjukkan pola yang sama. Di Italia, mafia Sisilia berkembang karena perlindungan pejabat lokal. Di Jepang, Yakuza bertahan karena relasi abu-abu dengan aparat. Di Kamboja, human trafficking dan judi online tumbuh pesat karena ada sebagian aparat keamanan yang terlibat.
Di Indonesia, fenomena ini muncul di banyak daerah. Di Nagekeo, ia menemukan bentuk paling telanjang. Begitu telanjang sehingga seorang aparat negara merasa lebih mudah menawarkan Rp150 juta kepada mahasiswa daripada menghadapi laporan dugaan tindak pidana. Orang jahat selalu mencri celah untuk menutupi kebusukannya sekaligus membungkam suara kritis yang berlawanan dengan kebohongannya.
Ketika sebuah institusi negara menolak membuka pintu bagi rakyat, itu bukan sekadar kesalahan prosedural. Itu adalah tanda bahwa sesuatu yang lebih dalam sedang berproses. Kita bisa membayangkan institusi seperti tubuh: ketika ia menolak fungsi-fungsi alaminya, itu berarti tubuh itu sedang sakit. Dan penolakan laporan oleh Polres Nagekeo menyingkapkan penyakit institusional yang jauh lebih serius: adanya jaringan kepentingan yang memanfaatkan tubuh negara demi keuntungan sebagian pihak.
Cengkeraman Mafia
Tidak ada kasus yang lebih menggambarkan betapa parahnya pembusukan institusional di Nagekeo selain sengkarut Waduk Lambo/Mbay. Proyek strategis nasional yang seharusnya membawa kesejahteraan justru berubah menjadi ladang permainan kelompok-kelompok tertentu.
Di sana, muncul “tuan tanah dadakan” yang tiba-tiba mengaku punya hak atas tanah yang sudah dihuni keluarga-keluarga adat selama puluhan tahun. Sertifikat terbit sambil lalu. Oknum pengacara bekerja sama dengan oknum aparat dan oknum pejabat desa untuk menciptakan cerita kepemilikan palsu. Di tengah semua itu, kelompok rentan-terutama pemilik tanah adat-menjadi korban paling awal dan paling besar. Mereka diiming-imingi uang kecil, diancam, atau dipinggirkan dengan manipulasi dokumen.
Tidak berhenti di situ, konflik tanah ini bahkan memakan korban jiwa. Ketika negara hadir, yang hadir bukanlah pelindung, tetapi bagian dari masalah. Sebagian bukti yang dibawa mahasiswa PMKRI justru menunjukkan pola rapi antara mediator tanah, oknum aparat, “calo proyek”, dan pemberi fee.
Dalam teori tindak pidana terorganisir, pola seperti ini disebut criminal collaboration with public authority: jaringan mafia yang tidak hanya memanfaatkan kelemahan hukum, tetapi memanfaatkan aparat sebagai bagian dari permainannya. Maka, ketika mahasiswa mengangkat isu mafia tanah ini, mereka sedang menyentuh saraf paling sensitif dari kekuasaan gelap.
Jika Anda berdiri di kawasan Galian C, Anda akan melihat deretan alat berat bekerja tanpa izin lokasi. Dengan hanya mengantungi IUP, para mafia bisa merajalela mengambil pasir di lahan yang bukan miliknya. Semuanya bisa dilihat dengan mata telanjang tanpa ada satu pihak pun yang mampu menghentikannya.
Dalam kriminologi, kondisi semacam ini disebut open secret criminality, kejahatan yang diketahui semua orang tetapi dibiarkan karena keterlibatan atau pembiaran aparat. Jika galian C ilegal bertahan bertahun-tahun, itu berarti ada perlindungan struktural. Tanpa itu, operasi semacam ini mustahil. Dan perlindungan struktural inilah yang membuat gerbang Polres ditutup ketika mahasiswa datang.
Penyelundupan hewan di Nagekeo bukan berita baru. Dalam satu malam, puluhan sapi bisa berpindah tangan. Sapi-sapi itu tidak berjalan sendiri. Tidak mungkin mereka berjalan dari kandang hingga ke kapal tanpa pengawasan aparat. Di banyak wilayah Indonesia, penyelundupan hewan sering kali dilakukan oleh jaringan yang melibatkan peternak, sopir, pengepul, dan oknum aparat yang memberi kenyamanan agar lalulintas ilegal berjalan mulus.
Di Nagekeo, mahasiswa mengungkap pola yang sama: hewan dipindahkan melalui jalur tertentu, ada biaya “keamanan”, ada koordinasi antara pelaku usaha gelap dan oknum aparat, dan ada pembiaran yang begitu lama hingga warga menganggap penyelundupan sebagai “hal biasa”.
Kejahatan yang menjadi hal biasa adalah tanda paling jelas bahwa negara sedang absen dari tugasnya. Atau lebih buruk: negara hadir, tetapi berpihak pada pelaku kejahatan.
BBM bersubsidi adalah barang strategis negara. Tetapi di banyak daerah, BBM bersubsidi menjadi komoditas mafia, dan Nagekeo tidak terkecuali. Solar yang seharusnya untuk nelayan dan petani menghilang dari SPBU. BBM bersubsidi itu dijual di Waduk Lambo dengan harga nonsubsidi. Ada bukti mobil pengangkut BBM yang diduga dibekingi oknum aparat polisi yang masuk dalam gerombolan mafia yang diotaki Serfolus Tegu, tertangkap di dalam waduk lokasi pintu masuk dereskit boadona.
Ketika mahasiswa membawa bukti ini dalam laporan resmi, Polres Nagekeo tidak hanya menolak menerima laporan, mereka bahkan menutup akses fisik ke kantor polisi. Dalam negara hukum, ini adalah anomali. Dalam negara yang institusinya masih mudah dibeli, ini adalah ritme biasa.
Tragedi Coklat Café adalah tragedi moral dan tragedi institusional. Empat pekerja seks dan satu polisi tewas akibat minuman beralkohol yang diduga tercampur bahan berbahaya. Tetapi yang jauh lebih tragis adalah bagaimana kasus itu menguap begitu saja tanpa penjelasan memuaskan. Café tempat kejadian disebut-sebut milik pejabat polisi sendiri. Bahkan rumor yang beredar menunjukkan keterlibatan oknum aparat dalam pengelolaan bisnis gelap hiburan malam.
Kasus yang seharusnya ditangani sebagai tindak pidana kesehatan dan kematian justru berhenti di tengah jalan. Ini bukan sekadar kelalaian. Ini adalah tanda bahwa aparat tidak pernah serius mengusut kasus yang menyentuh rumah mereka sendiri.
Dan inilah bagian paling menyakitkan dari semua ini: Warga yang seharusnya mendapat perlindungan justru menjadi korban. Aparat yang seharusnya menyelidiki justru menjadi bagian dari masalah.
Untuk memahami bagaimana mafia di Nagekeo bekerja, kita perlu menggunakan lensa akademik: konsep state-sponsored criminal network, jaringan kriminal yang hidup, tumbuh, dan bertahan karena adanya pembiaran atau keterlibatan aparat negara. Ada tiga elemen utamanya. Pertama, mafia tidak akan tumbuh jika negara kuat. Mafia muncul ketika negara lemah atau aparat dapat dibeli. Kedua, mafia membutuhkan “safe zone”, wilayah di mana mereka bebas bergerak tanpa takut ditindak. Safe zone ini hampir selalu disediakan oleh oknum aparat. Ketiga, mafia membutuhkan “gatekeeper”-penjaga pintu-yang memastikan laporan tidak naik, penyidikan tidak berjalan, dan bukti tidak mematikan.
Dalam kasus Nagekeo, gatekeeper itu telah diekspos secara tidak sengaja oleh tindakan Polres sendiri. Mereka menolak laporan, menolak dialog, menutup gerbang, dan mencoba membungkam mahasiswa dengan uang. Semua itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada keberanian mahasiswa itu sendiri. Bahaya terbesar bukan terletak pada mafia itu sendiri. Bahaya terbesar adalah ketika institusi negara-yang seharusnya melindungi warga-justru menjadi tawanan kepentingan mafia.
Dalam banyak kasus di negara lain-Kamboja, Meksiko, bahkan sebagian Filipina-kejahatan terorganisir berkembang karena aparat negara bukan hanya lalai, tetapi ikut bermain. Ketika itu terjadi, institusi negara berhenti berfungsi sebagai pelindung, dan berubah menjadi instrumen untuk memperkuat dominasi jaringan kejahatan. Nagekeo kini berada pada titik yang mirip. Ketika Polres menolak menerima laporan, itu bukan sekadar tindakan administrasi. Itu adalah sinyal bahwa institusi itu sedang disandera. Siapa yang menyeandera institusi Polres Nagekeo? Publik menduga sangat kuat bahwa yang menyendera Polres Nagekeo adalah kepala mafia untuk melindungi otak kejahatan mafia di Nagekeo.
DPRD Bungkam
Jika jaringan mafia telah beroperasi lama, itu berarti pengawasan politik tidak berjalan. DPRD mestinya menjadi pengawas eksekutif dan kepolisian di daerah, tetapi selama ini tidak terdengar suara kuat dari mereka dalam membongkar persoalan mafia. Pemda Nagekeo pun terlihat gamang: di satu sisi mereka ingin Waduk Lambo berjalan, tetapi di sisi lain mereka tidak ingin berhadapan dengan kekuatan yang memiliki akar dalam institusi keamanan. Publik paham bahwa Nagekeo dalam era kepemimpinan bupati saat ini, dilanda banyak masalah. Rupanya bupati kebingungan menentukan skala prioritas program kerjanya. Mungkin saja rakyat Nagekeo keliru menjatuhkan pilihan pada momen Pilkada.
Politik lokal di daerah sering kali bersifat patronase. Dalam patronase, keputusan tidak didasarkan pada hukum, melainkan pada hubungan kekuasaan. Dalam sistem seperti ini, aparat yang seharusnya netral menjadi bagian dari jejaring patron, bukan pelayanan publik. Maka tidak mengejutkan bila mahasiswa bertanya: “Bupati mau berpihak ke siapa? Polisi atau rakyat?” Pertanyaan itu tidak muncul dari ruang kosong. Itu adalah ringkasan rasa frustrasi warga selama bertahun-tahun.
Penyelamat Moral
Yang menarik dari seluruh peristiwa ini adalah bagaimana mahasiswa-yang sering diremehkan sebagai kelompok kecil tanpa kekuasaan-justru tampil sebagai kekuatan moral paling penting. Dalam sejarah di mana pun, mahasiswa selalu menjadi penjaga demokrasi ketika institusi lain gagal. Mahasiswa 1998 menggulingkan rezim. Mahasiswa 2019 menolak UU bermasalah. Mahasiswa Papua mengungkap diskriminasi. Mahasiswa PMKRI kini menantang mafia yang bersembunyi di balik institusi.
Keberanian mereka menolak suap Rp150 juta menjadi simbol bahwa integritas tidak pernah benar-benar hilang dalam masyarakat. Dan ketika mereka berdiri di depan gerbang Polres yang tertutup, mereka bukan hanya berdiri untuk diri mereka sendiri. Mereka berdiri untuk petani yang tanahnya dirampas, untuk nelayan yang kehilangan solar, untuk keluarga yang kehilangan ternak, untuk warga yang kehilangan anak, dan untuk publik yang kehilangan kepercayaan.
Pada titik tertentu, kita harus berhenti bertanya “Ada apa dengan mahasiswa?” dan mulai bertanya “Ada apa dengan institusi negara?”. Karena mahasiswa tidak berubah. Mereka hanya menjalankan peran moral yang diwariskan generasi demi generasi. Yang berubah justru institusi negara yang kini terlihat rapuh, defensif, dan mudah disandera kepentingan gelap.
Peristiwa di Nagekeo memperlihatkan bagaimana sebuah institusi yang seharusnya menjadi pilar negara-Polres-justru kehilangan keberanian untuk membuka pintu bagi rakyat. Ini bukan sekadar peristiwa lokal. Ini adalah cermin yang memantulkan wajah gelap negara ketika kekuasaan lokal tidak diawasi, ketika jaringan mafia menyusup, ketika moralitas aparat melemah, dan ketika fungsi hukum terbalik arah.
Dalam teori politik, negara tidak diukur dari besarnya gedung pemerintah atau jumlah aparat. Negara dinilai dari integritas moral petugas yang menjalankan kewenangan itu. Ketika aparat kehilangan integritas, negara runtuh dari dalam. Ia runtuh secara diam-diam, pelan, tetapi pasti dan masyarakat baru menyadarinya setelah terlalu banyak kerusakan terjadi.
Polres Nagekeo, dalam peristiwa ini, menunjukkan gejala-gejala tak terbantahkan dari institusi yang sedang runtuh secara moral: Mereka menolak laporan masyarakat, padahal hukum mewajibkan mereka menerima. Mereka menutup gerbang bagi rakyat, padahal anggaran negara membangun gerbang itu. Mereka mencoba menyuap mahasiswa, padahal suap adalah musuh profesi kepolisian. Mereka membiarkan mafia beroperasi, padahal polisi dibayar untuk memeranginya. Ketika aparat tidak lagi berpihak pada rakyat, negara berubah dari pelindung menjadi ancaman. Dan pada titik itulah, mahasiswa muncul sebagai pengingat keras bahwa negara sedang terluka.
Kita tidak boleh hanya menyalahkan aparat dalam situasi seperti ini. Ada struktur politik yang seharusnya mengawasi, tetapi diam. DPRD Nagekeo seharusnya menjadi suara rakyat dan pengawas eksekutif. Mereka memiliki hak interpelasi, hak angera, hak bertanya. Namun mereka tidak menggunakan satu pun kekuasaan itu untuk menyelesaikan persoalan mafia.
Pemda Nagekeo, yang seharusnya berani memimpin perubahan dan berpihak pada rakyat, justru terlihat ambigu. Bupati, wakil bupati, bahkan beberapa kepala dinas tampak berhitung secara politis ketimbang menjalankan mandat moral.
Kita sering lupa bahwa demokrasi membutuhkan lebih dari sekadar pemilu. Ia membutuhkan pemimpin yang berani mengatakan “tidak” pada kekuasaan gelap, dan “ya” pada integritas. Tanpa pengawasan politik yang kuat, aparat lokal dapat bertindak tanpa kontrol. Inilah yang terjadi di Nagekeo.
Menjadi Tembok, Bukan Jembatan
Polri selalu menegaskan bahwa mereka adalah pelindung dan pengayom masyarakat. Tetapi pada hari mahasiswa PMKRI berdiri di depan Polres, seragam itu berubah fungsi. Ia menjadi tembok yang memisahkan rakyat dengan negara. Ia menjadi baju besi yang melindungi aparat dari kritik, bukan melindungi rakyat dari ancaman.
Jika seragam dijadikan tameng untuk menutupi praktik mafia, bukan lagi menjadi lambang keadilan, maka seragam itu kehilangan kehormatannya. Dan kehormatan yang hilang tidak bisa dibeli dengan dana Polri, tidak bisa dipulihkan dengan kampanye humas, tidak bisa disembunyikan oleh seremonial serah-terima jabatan. Satu-satunya cara memulihkan kehormatan Polri adalah dengan kembali ke prinsip moral dasarnya: Polri ada untuk rakyat, bukan untuk dirinya sendiri.
Jika Polda NTT menganggap situasi ini kecil, mereka salah besar. Jika Mabes Polri menganggap ini persoalan lokal, mereka lebih keliru lagi. Karena apa yang terjadi di Nagekeo adalah cermin bagi seluruh Indonesia. Ia menunjukkan betapa mudahnya institusi strategis seperti Polri ditarik ke dalam jaringan mafia apabila tidak diawasi.
Kejadian Nagekeo harus menjadi momentum reformasi internal Polri: Pertama, Mabes Polri perlu membentuk tim investigasi independen untuk mengusut kasus suap Rp150 juta. Kedua, Polda NTT harus melakukan audit etika terhadap Kapolres dan Kabag Ops Serfolus Tegu. Ketiga, Propam harus memeriksa pola-pola pembiaran dalam kasus mafia tanah, hewan, galian C, dan BBM. Keempat, laporan mahasiswa PMKRI harus diterima, diverifikasi, dan diproses sesuai hukum. Kelima, Polri harus kembali pada prinsip dasar: mendengar rakyat sebelum mendengar siapa pun.
Tanpa langkah ini, Polri hanya akan menyisakan bangunan megah tanpa kepercayaan publik. Dan ketika kepercayaan publik hilang, tidak ada institusi negara yang dapat bertahan lama.
Ketika institusi formal gagal, masyarakat sipil harus bangkit. Warga Nagekeo perlu menyadari bahwa suara mereka memiliki kekuatan politik dan moral. Jangan menganggap mafia sebagai takdir. Jangan menganggap korupsi sebagai budaya. Dan jangan menganggap aparat sebagai penguasa yang tidak bisa dilawan. Media harus bersuara lebih lantang. Gereja, lembaga adat, dan tokoh masyarakat harus membawa isu ini ke ruang-ruang publik. Akademisi dan jurnalis perlu menyusun laporan independen. LSM harus mengadvokasi korban mafia tanah dan keluarga korban penyelundupan. Dengan tekanan publik yang konsisten, negara akan dipaksa untuk hadir.
Mahasiswa telah memberikan contoh. Kini giliran masyarakat. Karena aksi ini membuka tabir. Karena aksi ini menunjukkan retaknya benteng kekuasaan.
Karena aksi ini membuktikan bahwa mafia tidak kebal terhadap suara moral.
Karena aksi ini menunjukkan bahwa integritas masih ada di republik ini.
Mahasiswa PMKRI mungkin hanya belasan orang. Tetapi mereka melakukan apa yang tidak dilakukan institusi besar: membawa suara rakyat langsung ke pintu negara, meski pintu itu tertutup di depan wajah mereka.
Aksi kecil ini memiliki konsekuensi besar. Ia memaksa publik untuk bertanya: Jika mahasiswa diperlakukan seperti musuh, siapakah yang sebenarnya dilindungi aparat? Pertanyaan ini adalah pertanyaan paling berbahaya dalam negara demokrasi-berbahaya bagi pihak yang merasa terganggu oleh kebenaran.
Jangan Diam
Kita sering lupa bahwa negara bukan bangunan statis. Ia harus terus dirawat oleh moralitas, dikoreksi oleh rakyat, dan diperbaiki oleh keberanian warga sipil. Jika rakyat diam, negara akan perlahan disandera. Jika aparat korup dibiarkan, mafia akan tumbuh. Jika pelanggaran hukum dianggap biasa, hukum akan runtuh.
Nagekeo kini berada di titik kritis.Titik di mana publik harus memutuskan apakah mereka ingin masa depan di mana mafia memimpin dari balik layar, atau masa depan di mana institusi negara kembali menjalankan fungsinya secara benar.
Mahasiswa PMKRI telah menunjukkan jalan. Mereka datang dengan moralitas, bukan dengan kekerasan. Mereka datang dengan data, bukan dengan fitnah. Mereka datang dengan keberanian, bukan dengan ketakutan. Dan hari itu, mereka mengguncang kekuasaan yang jauh lebih besar dari mereka.
Mereka mengajarkan kita bahwa demokrasi tidak mati ketika institusi gagal.
Demokrasi mati ketika rakyat berhenti berjuang. Dan di depan gerbang Polres yang tertutup itu, demokrasi justru bangkit melalui keberanian belasan anak muda yang menolak suap, menolak bungkam, dan menolak menyerah.
Kini, bola ada di tangan kita semua-warga kritis, media, akademisi, Gereja, dan lembaga negara, yang masih memegang integritas. Jika kita memilih diam, mafia akan menang. Jika kita memilih bersuara, negara akan pulih. Dan sejarah selalu berpihak pada mereka yang berani.
Terakhir, jangan pernah takut ketika ada teror dan serangan pribadi dari orang lemah, pengacara mulut berbusa dan para pensiunan yang masih bernafas untuk membungkam sikap kritis ketika kita melawan terjangan dugaan mafia yang dipiara mereka. Perjuangan membela rakyat kecil yang ditindas di Rendu khususnya dan Nagekeo umumnya dalam beragam skala kasus adalah upaya memuliakan martabat kemanusiaan yang terluka ulah mafia. Nagekeo milik seluruh rakyat, bukan milik orang lemah yang pura-pura kuat hanya dengan sepotong kuasa tersisa dari masa lalu. *