Retret Mewah dan Kegagalan Empati Kepemimpinan
Oleh : Nia Liman
(Pegiat Literasi)
WARTA-NUSANTARA.COM-OPINI– Berita bahwa pejabat Pemprov Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar retret selama 10 hari di Unhan Belu dengan anggaran sekitar Rp 1 miliar jelas memicu keprihatinan publik. Pejabat eselon 2, 3, dan 4 dikabarkan ikut serta, dan meskipun tujuan retret itu diklaim sebagai forum refleksi, revitalisasi kepemimpinan, serta memperkokoh komitmen terhadap visi-misi pemerintah provinsi, tindakan ini menimbulkan pertanyaan penting: apakah pengeluaran semegah itu bermoral dan beretika di tengah kondisi masyarakat yang masih sangat menderita?



Opini publik pun bergejolak. Gelombang kritik yang muncul tidak hanya menyasar angka pengeluaran, tetapi juga menyentuh relung terdalam dari moralitas, etika, dan tanggung jawab kepemimpinan. Ini bukan sekadar masalah teknis atau administratif, melainkan sebuah tragedi moral yang memperlihatkan jurang pemisah antara realitas hidup pejabat dan rakyat yang mereka layani.


Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, hingga Maret 2025 persentase penduduk miskin di NTT masih 18,60%, atau sekitar 1,09 juta jiwa. Artinya, hampir satu dari lima orang di NTT hidup dalam kondisi miskin. Di sisi lain, dokumen APBD NTT 2023 memperlihatkan bahwa sebagian besar belanja daerah tersedot untuk belanja rutin: belanja operasi mencapai sekitar Rp 3,49 triliun, belanja barang dan jasa hampir Rp 1,49 triliun, sedangkan belanja bantuan sosial hanya sekitar Rp 44 miliar, angka yang jauh lebih kecil dibanding alokasi untuk kegiatan birokrasi. Dibanding angka-angka ini, Rp 1 miliar untuk sebuah retret pejabat memang terlihat kecil. Namun, di mata masyarakat miskin, jumlah itu bisa berarti ribuan paket sembako, puluhan beasiswa anak sekolah, peralatan medis vital yang sangat dibutuhkan di daerah terpencil atau puluhan unit sumur bor di desa-desa yang krisis air. Di tengah kondisi ekonomi yang sulit, angka 1 miliar memiliki kekuatan untuk mengubah banyak kehidupan. Tetapi, alih-alih mengalokasikan dana untuk kebutuhan-kebutuhan mendesak ini, prioritas justru jatuh pada sebuah acara internal yang esensinya adalah “menyenangkan” para pejabat.


Keputusan ini mencerminkan kegagalan fundamental dalam empati para pemimpin, yang seolah buta terhadap penderitaan di depan mata. Retret mewah ini menjadi simbol ironi yang menyakitkan: rakyat menderita, sementara para pemimpin yang seharusnya melayani mereka justru menikmati fasilitas eksklusif. Ini adalah narasi tragis tentang ketidakpedulian yang melukai hati nurani publik.


Dalam ilmu pemerintahan, etika publik adalah pilar utama. Prinsipnya sederhana: setiap tindakan dan pengeluaran pemerintah harus berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan umum. Namun, kasus retret ini menunjukkan adanya tafsir etika yang terpelintir. Pemerintah mungkin berdalih bahwa retret adalah investasi untuk meningkatkan kinerja tim, tetapi argumen ini rapuh. Etika yang sejati tidak hanya tentang efektivitas, tetapi juga tentang rasa keadilan. Menggunakan uang rakyat untuk kegiatan yang tidak mendesak, sementara hak-hak dasar rakyat terabaikan, adalah pelanggaran etika yang nyata. Tindakan ini adalah pengkhianatan terhadap amanah yang telah diberikan.


Seorang pemimpin memiliki tanggung jawab ganda: tanggung jawab fiskal dan tanggung jawab sosial. Tanggung jawab fiskal menuntut mereka untuk mengelola keuangan negara dengan bijak, efisien, dan transparan. Pengeluaran 1 miliar rupiah untuk retret adalah bukti nyata dari kegagalan dalam tanggung jawab ini. Lebih dari itu, tanggung jawab sosial seorang pemimpin adalah memastikan setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk hidup layak. Ketika sebagian rakyat terpuruk dalam kemiskinan, tugas pemimpin adalah mengangkat mereka, bukan malah mempertontonkan kemewahan. Retret ini bukan hanya memboroskan uang negara, tetapi juga meruntuhkan kepercayaan publik yang sudah rapuh terhadap pejabat daerah. Sekali lagi rakyat disuguhi bukti bahwa prioritas pemerintah seringkali berjarak dari kenyataan hidup mereka.
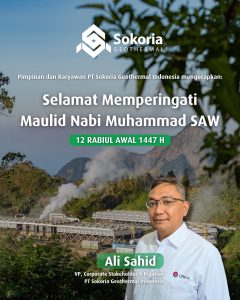
Tidak ada yang salah dengan refleksi kepemimpinan. Tetapi refleksi akan kehilangan makna bila dilakukan jauh dari rakyat, dalam ruang nyaman yang mengabaikan jeritan mereka. Retret kepemimpinan tidak harus berarti menyepi di balik dinding mewah dan fasilitas berkelas. Justru di tengah kemiskinan yang masih membelenggu banyak warga, pilihan paling bermakna adalah retret yang membumi, on the ground. Bayangkan bila para pejabat memilih untuk berkumpul di desa-desa miskin, tinggal bersama warga di rumah sederhana, atau menginap di daerah terpencil yang jauh dari listrik dan akses air bersih. Di sana, refleksi kepemimpinan lahir bukan dari materi seminar, melainkan dari perjumpaan nyata: tatapan seorang ibu yang bingung memberi makan anaknya, suara seorang nelayan yang resah karena harga ikan tak sebanding dengan biaya solar, atau curahan hati seorang guru honorer yang digaji tak cukup untuk hidup layak. Pengalaman semacam itu jauh lebih menyentuh dan membuka kesadaran. Dengan hadir secara langsung, para pemimpin tidak hanya mendengar laporan di meja rapat, tetapi juga merasakan sendiri denyut nadi persoalan yang dihadapi rakyatnya. Inilah retret yang sesungguhnya: sebuah perjalanan hati menuju pemahaman lebih dalam tentang penderitaan rakyat yang dilayani.
Tanpa empati, retret kepemimpinan hanya berubah menjadi liburan mewah dengan dalih refleksi. Anggaran Rp 1 miliar yang dihabiskan untuk fasilitas nyaman akan sulit diterima oleh rakyat yang setiap hari bergulat dengan kebutuhan dasar: makan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sederhana. Retret sejati bukanlah soal tempat atau kemewahan, melainkan keberanian untuk membuka diri terhadap realitas rakyat. Jika pemimpin sungguh ingin merevitalisasi kepemimpinannya, mereka harus mau menanggalkan kenyamanan, berjalan di jalan berlubang bersama warga, dan mendengar jeritan yang tak sampai ke ruang ber-AC. Kepemimpinan yang empatik lahir bukan dari kata-kata indah, melainkan dari telinga yang mau mendengar dan hati yang berani disentuh penderitaan rakyat. Tanpa itu semua, retret hanya akan dikenang sebagai kegagalan empati di tengah krisis kemanusiaan yang nyata. ***








