Luka Anak dan Dosa Sosial Kita; Menggugat Budaya Malu di Balik Kekerasan Seksual Terhadap Anak
Oleh : Nia Liman
(Pegiat Literasi)
WARTA-NUSANTARA.COM– Mari kita bicara jujur, apa adanya. Kasus kekerasan seksual pada anak seperti yang sering terjadi di Lembata dan di mana saja, sebenarnya bukan lagi berita. Itu sudah jadi semacam rutinitas yang mengerikan. Kita lihat data angkanya di berita: naik, turun sebentar, lalu naik lagi. Kepolisian Resor Lembata mencatat sepanjang tahun 2025 hingga September kemarin ada sebanyak 13 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Jika dirata-rata, berarti setiap bulan ada lebih dari satu anak yang menjadi korban. Gambaran di Lembata ini sejalan dengan kondisi provinsi NTT secara keseluruhan. Pada 2024 tercatat sekitar 1.700 laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan 60 persen korbannya adalah anak-anak. Artinya, setiap kali kita mendengar kabar kekerasan seksual, kemungkinan besar korban adalah seorang anak.





Yang paling menyakitkan dari semua kasus ini adalah pelakunya. Jarang sekali pelakunya adalah orang asing yang tiba-tiba muncul di malam hari atau di tempat sepi. Selalu saja orang yang dikenal, orang yang dipercaya: paman, tetangga, guru, kadang malah ayah atau kakek kandung. Ini berarti ruang aman kita sudah runtuh. Rumah, yang seharusnya jadi benteng terakhir, sudah jadi tempat paling berbahaya. Sekarang mari kita refleksi. Kenapa ini bisa terjadi terus-menerus?



Refleksi pertama: budaya diam yang mematikan. Kita hidup dengan budaya “malu”. Di Lembata, seperti di banyak tempat, kekerasan seksual itu dianggap aib keluarga yang memalukan. Akhirnya, kasus tidak dilihat sebagai kejahatan yang harus dihukum, tapi sebagai masalah yang harus ditutupi. Begitu ada kasus, korban disuruh diam, keluarga menutup mulut rapat-rapat, dan yang didahulukan adalah negosiasi, “damai,” atau “selesaikan secara adat.” Budaya malu ini membuat banyak kasus tidak pernah sampai ke polisi atau pengadilan. Korban kehilangan haknya atas keadilan sementara pelaku tetap aman karena dia tahu masyarakat lebih takut pada gunjingan tetangga daripada penderitaan anak. Sangat ironis bahwa kita sebagai masyarakat yang seharusnya jadi pelindung korban, justru jadi tembok yang melindungi si penjahat. Setiap kali kita memilih damai atau pasif, kita sebenarnya mengizinkan predator itu mencari korban berikutnya dan mengulang perbuatannya. Di situlah kita ikut bertanggung jawab, sebab kita yang memberi mereka izin bebas lewat sikap diam kita. Diam tak selamanya emas. Diam justru sering kali adalah pengkhianatan. Pengkhianatan ini bukan hanya terhadap anak yang terluka, tetapi juga terhadap hati nurani kita sendiri yang seharusnya menuntut keadilan.


Refleksi kedua: kita tidak boleh lelah melindungi anak-anak. Kita mungkin capek dengan berita buruk, capek dengan masalah ekonomi, capek dengan hidup. Tapi terhadap anak-anak kita tidak boleh capek. Anak-anak tidak pernah meminta untuk dilahirkan ke dunia. Mereka tidak memilih untuk lahir dan tumbuh dalam lingkungan yang menakutkan. Saat kita malas melapor, malas mengedukasi diri, atau malas mendesak polisi mengurus persoalan kekerasan terhadap anak, kita sedang membebankan rasa capek kita pada trauma anak. Padahal sesungguhnya tanggung jawab itu sepenuhnya milik kita orang dewasa. Mau sekaya atau semiskin apa pun kita, kewajiban melindungi anak itu harga mati. Kalau kita gagal melindungi anak, kita sebenarnya gagal jadi manusia. Sebab, inti dari kemanusiaan adalah kepedulian pada yang paling lemah dan rentan. Maka, setiap kali ada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, sesungguhnya yang runtuh bukan hanya hidup satu individu, tetapi juga martabat sebuah masyarakat. Apa arti kita menyebut diri “manusia” bila kita tega membiarkan anak-anak hidup dalam luka yang akan mereka bawa seumur hidup?


Refleksi ketiga: siapa sebenarnya yang kita lindungi? Ketika kasus ditutup-tutupi, coba tanya diri sendiri: Siapa yang sebenarnya kita lindungi? Apakah kita melindungi anak yang trauma, atau kita melindungi reputasi si pelaku? Seringkali, jawabannya adalah yang kedua. Kita memilih mengabaikan luka anak demi menjaga nama baik keluarga. Lantas apa gunanya menjaga nama baik keluarga jika yang dikorbankan adalah jiwa anak sendiri? Aib bisa dilupakan orang, tetapi luka anak akan terus hidup dalam diam sepanjang hidupnya. Kita rela menukar masa depan anak hanya demi ketenangan meja makan keluarga. Kita lebih mudah membungkam anak daripada membongkar kebusukan di dalam keluarga sendiri. Demi reputasi, kita tega meninggalkan anak sendirian dalam gelap traumanya. Kita sibuk menutup mata agar keluarga tampak utuh, padahal di dalamnya ada anak yang retak. Dan tragisnya, anak-anak dipaksa menanggung beban luka, hanya karena orang dewasa lebih takut pada gosip ketimbang pada kebenaran. Prioritas moral kita telah terbalik. Kita menempatkan ego komunal (nama baik) di atas keselamatan individu (anak), dan inilah kegagalan moral paling mendasar dari masyarakat. Masyarakat yang beradab adalah masyarakat yang punya keberanian untuk menjaga anggotanya yang paling rentan, yang setia melindungi jiwa-jiwa kecil yang mempercayakan hidupnya kepada kita.


Lantas harus bagaimana? Solusinya tidak hanya menambah tahun hukuman penjara bagi para pelaku. Yang kita butuhkan adalah membangun kembali kesadaran kolektif bahwa melindungi anak itu adalah tanggung jawab moral tertinggi semua orang. Kita harus berhenti bersikap pasif. Kita mesti membongkar “sistem diam” yang selama ini kita pelihara bersama. Kita harus jadi orang yang cerewet, yang berani melapor, yang berani bersuara di depan pemuka adat atau kepala desa setiap kali mengetahui masalah kekerasan terhadap anak. Bukan karena kita sok pahlawan, tapi karena kita harus menghentikan mata rantai kejahatan ini.


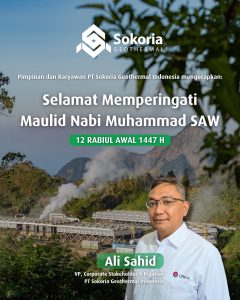
Kita memang tidak bisa mengendalikan nafsu atau hasrat seksual orang lain. Tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana masyarakat merespons, bagaimana hukum ditegakkan, dan bagaimana anak-anak dilindungi. Perlindungan anak harus dimulai dari rumah, diperkuat di sekolah, dijaga ketat oleh komunitas, dan dijamin oleh negara. Budaya diam harus diganti dengan keberanian untuk bersuara. Aparat penegak hukum harus memastikan setiap pelaku dihukum tanpa pandang bulu, termasuk bila pelaku berasal dari lingkaran keluarga atau darah daging sendiri. Dengan begitu kita bisa memutus rantai kekerasan seksual terhadap anak, dan menunjukkan bahwa martabat manusia lebih tinggi daripada gengsi keluarga, dan bahwa keadilan lebih penting daripada aib yang ditutupi.
Mengabaikan kekerasan seksual pada anak adalah dosa sosial yang tidak termaafkan. Sebab, dengan memilih diam artinya kita mengkhianati anak-anak, dan mengkhianati anak berarti menggadaikan masa depan sebuah bangsa. Ukuran sederhana untuk menilai tingginya peradaban sebuah bangsa ialah bagaimana ia memperlakukan anak-anaknya. Jika masyarakatnya gagal melindungi anak-anak, maka ia sedang membiarkan fondasi masa depannya runtuh. Tanggung jawab kita kini jelas: bertobat dari dosa sosial ini dengan berani bersuara dan memastikan keadilan ditegakkan, tanpa ada lagi kompromi. Negara tidak boleh ragu, masyarakat tidak boleh bungkam, dan keluarga tidak boleh abai. Hanya ketika kita menempatkan perlindungan anak sebagai prioritas tertinggi, barulah kita bisa menyebut diri sebagai manusia yang beradab, serta membangun sebuah peradaban yang sungguh-sungguh berpihak pada kehidupan.







