RINDU RUMAH
Ide Inspiratif dari Lukas 10: 1 – 12. Homili Pesta Santo Josef Freinademetz, 29 Januari 2026
Oleh : Robert Bala
WARTA-NUSANTARA.COM– Lagu “Rindu Rumah” ciptaan Andi Sechil Tuharea dan dipopulerkan Wizz Baker (juga duet bareng Gihon Marel) rasanya kena banget di hati. Lagu ini seperti punya tombol rahasia: sekali diputar, langsung narik kita pulang—bukan cuma ke tempat, tapi ke perasaan. Apalagi setelah masa pandemi, lagu ini terdengar makin relevan.
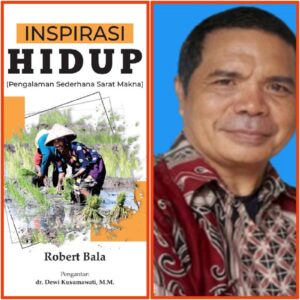
“Rumah” di sini bukan sekadar bangunan. Rumah adalah tempat di mana kita bisa jadi diri sendiri. Tempat di mana kita dikenal apa adanya. Tanpa topeng. Tanpa pencitraan. Tanpa harus membuktikan apa pun. Kalau jadi tempat, maka rumah adalah tempat di mana hatimua berada:
Rindu rumah aku rindu pulang
Rindu yang tersayang ayah dan ibu
Rindu rumah aku rindu pulang
Rindu ku disayang sanak saudara
Rindu rumah hampir selalu berarti rindu orang-orang di dalamnya: keluarga, sahabat, kenangan, dan kehangatan relasi. Rindu rumah muncul ketika kita lelah menjadi “perantau hidup”—lelah harus kuat terus, lelah harus kelihatan baik-baik saja.
Nada rindu yang sama juga kita temukan dalam kisah seorang misionaris SVD, Santo Josef Freinademetz. Di usia 26 tahun, ia meninggalkan kampung halamannya di Tyrol dan pergi jauh ke Cina. Jaraknya bukan cuma soal kilometer, tapi soal budaya, bahasa, cara hidup, dan cara berpikir yang sangat berbeda.
Bisa dibayangkan betapa beratnya. Pergi ke Cina berarti masuk ke dunia yang asing. Semakin berbeda budaya, semakin mungkin terjadi kesalahpahaman. Di sana manusia bisa menjadi serigala yang lain. Tak heran Yesus saat mengutus para muridNya ia berpesan: “Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala” (Luk 10:3). Ketakutan itu nyata. Apalagi jika seseorang datang dengan sikap merasa lebih tahu, lebih benar, atau membawa keangkuhan budayanya sendiri. Benteng penolakan pasti langsung dibangun. Ia datang dengan pundi-pundi penuh dan merasa tanpa penerimaan pun ia bisa hidup.
Namun Freinademetz memilih jalan yang radikal. Ia berkata tegas kepada rekan-rekannya:
“Aku ingin menjadi orang Cina, dan mati sebagai orang Cina.” Ini bukan kalimat romantis. Ini keputusan hidup. Ia berangkat tahun 1878 dan wafat tahun 1908—30 tahun di Cina, tanpa pernah kembali secara fisik ke tanah kelahirannya. Ia pulang, tapi dengan cara lain: sebagai teladan. Ia mau masuk dan menjadi bagian dari orang yang dilayani. Sebuah cinta radikal.
Apa kuncinya?
Pertama, Freinademetz tidak datang sebagai tamu yang mampir, tapi sebagai penghuni yang tinggal. Ia menjalani sabda Yesus: “Tinggallah dalam rumah itu… jangan berpindah-pindah” (Luk 10:7). Tinggal berarti belajar mengakar. Belajar merasa, berpikir, dan mencintai seperti tuan rumah.
Ia belajar bahasa Cina dengan susah payah, sering salah paham, sering kesepian. Tapi justru di situ ia pelan-pelan menemukan rumah baru. Semakin keras tantangan, semakin ia berani masuk lebih dalam. Rasa seperti di rumah sendiri inilah yang menjadi fondasi tetapi sekaligus menjadi akar dari banyak persoalan. Banyak orang yang hanya sebagai pendatang: mengambil kekayaan kemudian meninggalkan duka dalam bentuk bencan alam. Banjir bandang, longsor, hanyalah bekas dari mereka yang hanya sebagai pendatang. Bukan penghuni tetap.
Kedua, Freinademetz justru datang dan menjadi seperti orang Cina. “Saya ingin hidup dan mati seorang orang Cina. Keputusan ini merupakan ekspresi nyata dari sebuah inkulturasi sejati—bukan sebagai strategi, tapi sebagai wujud kasih. Freinademetz tidak datang untuk “mengubah” orang Cina, tetapi untuk mencintai mereka. Ia mencintai budaya, cara berpikir, bahkan penderitaan mereka. Injil tidak dipaksakan dari luar, tetapi tumbuh dari dalam kehidupan umat.
Karena cinta maka ia berusaha agar Cina menjadi seperti rumahnya sendiri. Awalnya sudah tetapi perlahan diterima tidak saja sebagai bagian tetapi juga sebagai pilar yang terasa kurang kalan tanpanya, apalagi kalau ia kembali.
Ketiga, ia juga matang secara batin. Ia tahu bahwa tidak semua orang akan menerima. Dan itu tidak membuatnya pahit. Ia tidak reaktif, tidak menyimpan luka berkepanjangan. Ia tetap setia. Sampai akhir hidupnya. Ia wafat di Cina, bukan sebagai orang asing, tapi sebagai bapak rohani.
Di sinilah kita bercermin. Banyak dari kita mudah lelah, mudah kecewa, dan akhirnya merasa “tunawisma”—tidak sungguh masuk ke tempat baru, tapi juga tidak lagi merasa pulang. Kita singgah, mampir, lalu pergi. Freinademetz justru menemukan dua hal sekaligus: rindunya tetap ada, tapi ia juga merasa betah karena diterima.
Pesta Santo Josef Freinademetz, 29 Januari—hari wafatnya—mengingatkan kita bahwa rindu rumah bukan sekadar nostalgia. Rindu rumah adalah panggilan: untuk menciptakan rasa “at home” di mana pun kita berada.
Ini juga jadi kritik sosial. Banyak kerusakan terjadi karena orang merasa hanya singgah, bukan tinggal: deforestasi, banjir bandang, eksploitasi alam. Yang datang mengambil, bukan merawat.
Semoga teladan Santo Josef Freinademetz menolong kita: agar kita sungguh belajar tinggal, mencintai, dan menciptakan rumah—di keluarga, lingkungan, paroki, keuskupan, dan negeri kita sendiri.
Sebuah ajakan yang tidak mudah. Tetapi dari pengalaman Josef Freinademetz, kita diingatkan bahwa rindu rumah tidak harus kembali secara fisik. Rindu rumah mendorong kita agar dengan car akita masing-masing dapat menciptakan suasana rumah, at home, sebagai tempat di mana hati kita berada. ***
Robert Bala. Penulis buku Inspirasi Hidup. Pengalaman Kecil Sarat Makna. Penerbit Kanisius Yogyakarta, Cetakan ke-2.









